Cerpen | DETaK
Pukul 8 malam, langit kota Paris dipenuhi gemerlap bintang, jalan-jalan diterangi pendar lampu yang memancarkan cahaya kuning lembut. Aku menjejakkan kaki di sepanjang tepi sungai Seine, kuperhatikan siluet bangunan-bangunan klasik seperti Notre Dame atau Menara Eiffel tercermin di air. Restoran-restoran dan kafe-kafe di sudut-sudut jalan menyajikan pemandangan yang ramai dengan orang-orang menikmati makan malamnya beserta segelas bir di luar ruangan. Paris di malam hari memang memiliki pesona yang sangat khas, dengan gabungan antara arsitektur yang indah, suasana yang romantis, dan kesan sejarah yang kuat.
Selagi berjalan, sesekali kulirik layar handphone yang menampilkan Gmaps menuju kafe yang aku dan salah satu teman lamaku telah sepakati untuk berjumpa di sana, nama kafenya Les Deux Magots, salah satu kedai kopi tertua di Paris, yang sangat terkenal karena telah menyaksikan banyak wisatawan yang kelaparan dan kurang tidur, bersama dengan tokoh-tokoh terkenal Prancis. Filsuf, penulis, dan seniman terkenal seperti Pablo Picasso, Albert Camus, dan Jean-Paul Sartre yang telah duduk menghiasi kursinya.

Aku sendiri belum lama di Paris, seingatku baru 3 bulan. Setelah lulus S1, ibuku memaksaku untuk melanjutkan S2 di Eropa agar bisa mendapatkan menantu bule katanya. Dan pilihanku jatuh pada Paris sang kota cinta, walaupun sebenarnya aku pergi ke sini bukan untuk mencarikan ibuku menantu, melainkan karena kecintaanku pada sesuatu yang berbau klasik, musik contohnya. Paris di penuhi dengan para musisi jalanan, mereka bahkan bisa memainkan alat musik mereka dari pagi sampai malam dan kita bisa menontonnya hampir di setiap sudut jalan, inilah yang kusuka dari kota romantis ini.
Kulirik jam tangan, pukul 8.15, akhirnya aku tiba di depan Les Deux Magots, sebenarnya kami berjanji untuk bertemu pukul 9 malam, namun sepertinya aku terlalu bersemangat hingga datang secepat ini. Aku langsung menuju ke pintu kedai dan membukanya, seketika kurasakan aroma kopi yang harum memenuhi udara. Di dalam, suasana tenang dengan lampu redup menggantung di langit-langit kayu. Musik jazz mengalun lembut dari sudut panggung kecil di pojok ruangan dengan cahaya lampu sorot menyoroti grup musik yang sedang tampil di sana.
Di meja-meja kayu yang tertata rapi, terdapat orang-orang yang sedang menikmati gelas-gelas anggur atau segelas kopi, sambil terlena dengan alunan musik yang mengalun dengan lembut. Beberapa pasangan duduk berhadapan, berbicara dengan suara yang hampir merdu, tertular oleh romantisme dan keanggunan Paris. Aku memilih salah satu meja yang berada di samping jendela dan duduk menunggu di sana, salah satu pramusaji menghampiriku untuk menanyakan pesanan.
“Un cappuccino sans sucre, s’il vous plait”
Aku memesan satu cappuccino tanpa gula dan merasa bangga berhasil mengatakannya dalam bahasa Prancis yang dinobatkan sebagai salah satu bahasa tersulit di dunia, pramusaji tersebut tersenyum sebelum beranjak meninggalkan mejaku, sepertinya ia menertawakan aksenku yang masih berantakan dalam hatinya. Aku balas tersenyum, mengabaikan seringainnya dan mengalihkan pandanganku kepada kelompok musisi yang membawakan music jazz di sudut ruangan sana. Ah…ini dia favoritku, ayunan bow pada biola, petikan jari pada gitar, dan melodi khas yang dikeluarkan piano selalu membuatku terpesona, meskipun aku bukan mahasiswa seni, tapi aku sangat menyukai seni. Dan musik, selalu menjadi seni favoritku.
Seorang penyanyi berdiri tegak di atas panggung kecil yang diterangi oleh lampu sorot yang lembut. Dia mengenakan gaun malam yang elegan, dengan warna yang melengkapi suasana romantis dari lagu yang dia nyanyikan. Begitu mendengar alunan musiknya aku langsung tau band ini sedang membawakan lagu Paris Love Lovers, sebuah lagu khas Paris yang sudah sering kudengar, lagu ini paling menonjolkan suara gesekan biola, yang membuat pandanganku langsung beralih dari sang penyanyi menuju seorang pria yang memainkan biola di belakangnya.
‘dia sangat berbakat’ gumamku pelan.
Melihat pria itu menggesekkan biolanya dengan handal, aku jadi teringat kepada pasar di kampung halaman, kenapa pasar? Karena dulu saat aku masih kecil, aku sering diajak ke pasar oleh ibuku untuk membantunya membawa plastik belanjaan. Dan mungkin, dari sanalah kecintaanku pada musik tumbuh, jauh sebelum aku memilki paspor untuk menjelajahi dunia, jauh sebelum aku bisa memegang tiket konser opera, bahkan jauh sebelum aku bisa menikmati banyak pertunjukan musik resital, di sana, di sudut pasar, ada seorang kakek yang tidak bisa melihat dengan tubuh kurus dan ringkih memainkan biolanya dengan semangat.
Saat itu mungkin aku baru kelas 2 SD, aku memperhatikan kakek yang bermain biola itu dengan penuh pertanyaan, mata kakek itu terpejam sebelah dan yang sebelah lagi semuanya berwarna putih, ia duduk dengan kaki bersila di atas sebuah alas yang sepetinya sejenis goni beras, di depannya ada sebuah wadah kecil untuk orang meletakkan uang, tangan sebelah kanannya memegang bow biola dan yang satunya lagi menopang biola ukuran kecil di bahunya. Aku melihat kakek itu dengan perasaan bercapur aduk, antara bingung, kasihan, dan takjub. Aku sendiri tidak tau melodi apa yang ia mainkan, itu tidak terdengan seperti lagu, tapi nadanya masih membentuk sebuah ritme musik. Namun, aku tidak bisa menikmati permainan biola kakek itu dengan lama, karena ibuku selalu menyeret tanganku setiap kali ia selesai membeli sayur yang ada di depan tempat kakek itu duduk.
Sepulang dari pasar aku selalu bertanya-tanya, bagaimana cara kekek itu belajar biola dengan mata yang tidak bisa melihat, bagaimana ia bisa memiliki biola jika ia tidak punya uang, yang mana biola itu masih terlihat sangat bagus walau sedikit kusam.
Bertahun-tahun berlalu, aku beranjak dari SD, SMP, dan SMA, setiap kali aku pergi ke pasar menemani ibu belanja, kakek itu masih duduk di sana, memainkan biolanya dengan takzim tanpa memperdulikan suasana pasar yang riuh, kondisinya masih sama, bahkan seperti sama sekali tidak ada yang berubah, bajunya, karung goninya, wadahnya, hanya saja tubuh kakek itu terlihat semakin kurus dan ringkih, matanya sudah sepenuhnya terpejam, dan ia, masih memainkan biolanya yang semakin kusam termakan usia, namun tidak ada yang berubah dari permainan biola kakek itu, nadanya masih sama, suaranya pun masih sama. Aku bertanya-tanya sembari mengeluarkan uang dua ribuan dari sakuku hari itu, pernahkah senar biolanya itu copot atau bahkan putus?
Mungkin jika diberikan waktu, aku ingin duduk di samping kakek itu, bertanya-tanya tentang masa mudanya, mungkin kakek ini dulunya adalah seorang musisi yang sangat terlatih, atau bahkan ia dulunya sudah pernah menciptakan banyak lagu dengan biolanya ini, atau mungkin tampil di banyak acara-acara besar, namun alih-alih bercakap-cakap, aku hanya menghampiri kakek itu untuk meletakkan uang dua ribuan sisa uang kembalian dari sakuku ke wadah kecil yang ada di depannya.
Dan sepertinya kakek itu tidak pernah tau jika ada orang yang meletakkan uang di wadahnya, ia tetap lanjut memainkan biolanya seperti tidak ada yang terjadi, waktu itu aku berdoa dalam hati ‘semoga kakek sehat selalu dan diberikan umur panjang’ sebelum tersenyum dan pergi menyusul ibuku yang sudah berkali-kali memanggil namaku untuk membantunya membawa plastik belanja yang berat.
“Rez.. Reza… Hai… kamu mikirin apaan sih? Serius banget”
Lamunanku seketika buyar, aku mengedipkan mataku beberapa kali untuk kembali ke kenyataan, dan di depanku telah berdiri seseorang yang sudah lebih dari setengah jam lalu kutunggu, sahabatku sewaktu SMA dulu, namanya Rangga, ia telah tinggal di Paris selama 3 tahun karena berhasil menjadi manajer di salah satu perusahaan mode Paris.
“Rangga! Apa kabar?!”
“Very Good Bro!”
Kami saling beradu tos dan berpelukan, rasanya sudah sangat lama kami tidak bertemu satu sama lain, tidak pula saat reuni sekolah karena Rangga selalu sibuk dan hampir selalu berada di luar negeri, detik berikutnya kami sudah tenggelam dalam obrolan hangat tentang kenangan lama dan perjalanan hidup sejauh ini, dengan latar belakang musik jazz dan secangkir kopi panas di tangan, dan waktu berjalan sangat cepat saat dihabiskan bersama teman.
***
“ Reza! tolong pergi ke pasar, daftar belanjanya sudah ibu letakkan di atas meja makan, jangan lupa ya! Ibu harus membantu ibu Roni untuk acara aqiqah cucunya besok”
Aku menggosok mataku perlahan dengan punggung tangan, baru juga bangun tidur, ibu sudah memberikan pekerjaan padaku, aku melihat daftar belanjaan yang tidak terlalu panjang itu di atas meja makan dengan mata memicing, tiba-tiba sebuah tepukan kencang mendarat di punggung ku, membuat ku meringis kesakitan.
“Aduh! Buk…”
“Jam segini baru bangun! Hadeuh… teman-teman ibu semua udah pada mau punya cucu, kamu masih aja, udah ah, jangan lupa itu semua dibeli ya!”
Ibuku menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum beranjak keluar rumah menuju rumah bu Roni, tentangga kami yang akan membuat acara aqiqah besok. Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal, ibuku tidak ada bedanya, masih saja suka mengomel.
Sudah dua tahun berlalu tanpa terasa dan setelah berhasil melewati proses mengerjakan tesis yang panjang, aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman selagi menunggu hasil tesisku keluar. Dan tanpa banyak pikir lagi, aku bergegas ke kamar mandi untuk bersiap menuju ke pasar.
Sesampai di pasar, aku melihat kertas yang berisi daftar belanjaan yang telah ibu tulis dan bergegas membeli barang yang diperlukan satu per satu, begitu aku selelsai membeli sayur, aku melihat ke sudut pasar, tempat kakek pemain biola biasa berada, aku mencoba membayangkan tampilan si kakek setelah sekian lama aku tidak melihatnya, karena memang semenjak kuliah ke luar kota, aku sangat jarang pergi ke pasar, ini mungkin yang pertama kalinya setelah dua tahun berada di luar negeri. Dan saat aku melihat sudut pasar itu, betapa terkejutnya aku, bahwa yang duduk di situ bukan lagi si kakek pemain biola, melainkan pengemis biasa yang menadahkan tangannya meminta sedekah. Kemanakah kakek itu?
Aku mencoba bertanya kepada penjual sayur yang lapaknya memang berhadapan dengan sudut pasar itu, namun sang penjual sayur menjawab tidak tau, ia juga baru sadar bahwa kakek itu sudah tidak ada di situ. Aku semakin bingung, kucoba bertanya dengan penjual telur yang juga berada disebelahnya, namun bapak itu juga menjawab tidak tau, aku mengerutkan dahi, mungkin kakek itu sudah pindah tempat, atau sudah pulang ke rumah keluarganya, atau…
“Kakek itu sudah meninggal tiga tahun lalu”
Tiba-tiba seorang gadis berkerudung merah muda sudah berdiri di sampingku dengan pandangan lurus kedepan, melihat sudut pasar tempat kakek itu dulu memainkan bioalnya. Aku menatap gadis itu tidak percaya.
“Apa?”
“Kakek itu meninggal pada sore hari dengan posisi membungkuk dan tangan menggenggam erat biolanya, tidak banyak orang yang mengetahui kehilangannya karena saat sore hari pasar mulai sepi, dan hanya beberapa orang saja yang tahu, lagian.. kakek itu juga bukan siapa-siapa sehingga orang tidak ada yang mengingatnya, ia hanya pengamen biasa” kata gadis itu datar, ia lalu mengalihkan pandangannya untuk memilih telur-telur yang sekiranya bagus.
Aku menatap sudut pasar itu tidak percaya, tanpa kusadari cairan bening mulai mengaburkan pandanganku, jadi.. penampilan biola kakek itu sudah berakhir 3 tahun lalu. Gadis itu benar, kakek itu memang bukan siapa-siapa dan hanya pengamen biasa, namun di hatiku kakek itu lebih dari sekedar pengamen, dulu karena melihat biolanya itulah yang membuatku tertarik pada musik-musik orchestra, dan membuatku membuka mata lebih lebar pada seni, memang hanya hal yang kecil, namun tetap saja hal itu menyimpan kenangan yang khusus tidak hanya di sudut pasar ini, namun juga di sudut hatiku.
Aku menghela nafas pelan, lantas mengeluarkan selembar uang dua ribuan hasil kembalian beli sayur tadi, lalu aku pergi ke sudut pasar dan meletakkannya di atas tangan pengemis yang duduk di tempat kakek pemain biola duduk dulu, aku lantas beranjak pergi, ingin segera menyelasaikan daftar belanjaan ini.[]
Penulis adalah Zarifah Amalia, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Syiah Kuala. Ia juga merupakan anggota magang di UKM Pers DETaK USK.
Editor: Masya Pratiwi

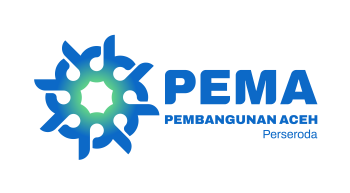


![Melodi Hujan di Bulan September Amirah Nurlija Zabrina [AM]](https://detakusk.com/wp-content/uploads/2024/09/ILUSTRASI-CERPEN-238x178.png)







