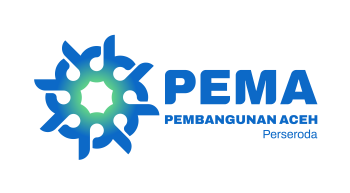Cerpen | DETaK
Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Langit seolah menumpahkan seluruh kesedihannya di atas desa kecil yang selama ini dikenal damai. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, hanya hujan yang jatuh terus-menerus, seperti tak ingin berhenti. Jalan tanah berubah licin, parit-parit kecil mulai penuh, dan halaman rumah perlahan digenangi air.
Tak ada yang curiga. Hujan sudah terlalu sering datang akhir-akhir ini. Orang-orang menganggapnya biasa. Mereka menutup pintu, menarik jendela, lalu merebahkan badan setelah seharian bekerja. Ada yang masih berbincang dengan keluarga, ada yang menidurkan anak-anaknya sambil menepuk punggung pelan, dan ada pula yang langsung tertidur karena lelah.

Di benak mereka, hari esok akan sama seperti kemarin. Bangun pagi, bekerja, pulang, dan menjalani hidup sederhana yang itu-itu saja. Tak ada yang menyangka, malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya.
Namun malam selalu punya caranya sendiri.
Air datang perlahan. Menyusup lewat sela tanah, masuk ke halaman rumah, merayap tanpa suara. Awalnya hanya setinggi mata kaki. Beberapa orang masih sempat tertawa kecil, mengangkat celana, dan berpikir air itu akan segera surut seperti biasanya. Anak-anak malah sempat bermain, mencipratkan air dengan kaki kecil mereka.
Tapi air tidak berhenti.
Dalam gelap, genangan itu tumbuh cepat. Ia naik, berlari, dan membesar tanpa ampun. Air mulai masuk ke rumah-rumah, membawa lumpur, ranting, dan benda-benda kecil. Lantai terasa dingin dan asing. Bau tanah basah bercampur lumpur memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, lampu padam. Desa tenggelam dalam gelap.
Suara retakan kayu terdengar bersahutan. Lemari rubuh, kursi terseret arus, dan benda-benda jatuh tanpa bisa dicegah. Teriakan panik mulai terdengar di mana-mana. Nama-nama dipanggil berulang kali, dengan suara yang semakin meninggi dan putus-putus.
Di tengah genangan, mereka bergegas menyelamatkan yang paling berharga. Bukan harta, bukan pula barang. Anak-anak digendong seadanya, orang tua dituntun perlahan, saudara dicari dalam gelap. Mereka hanya peduli pada siapa yang masih bisa mereka panggil dan jawabannya masih terdengar.
Tangis, doa, dan teriakan bercampur menjadi satu. Ada yang memeluk anaknya sambil menangis tanpa suara, ada yang berteriak memanggil nama orang tuanya yang terpisah arus. Air tak mengenal belas kasihan. Ia terus naik, menelan apa pun yang ada di jalurnya.
Malam itu, tak ada yang benar-benar siap. Tak ada yang sempat berpikir panjang. Tidak ada rencana, tidak ada strategi. Yang ada hanya satu keinginan: bertahan sampai pagi.
Ketika fajar akhirnya datang, desa itu tak lagi sama.
Air masih mengalir, seolah belum puas melampiaskan amarahnya. Rumah-rumah nyaris tak terlihat. Hanya atap dan ujung genteng yang muncul di antara genangan cokelat. Jalan lenyap, batas antara sungai dan pemukiman menghilang. Desa yang dulu hidup, kini seperti berhenti bernapas.
Hari berganti hari. Air masih menggenang di desa itu. Waktu terasa berjalan lambat. Orang-orang menunggu dengan cemas, berharap air segera surut. Hingga pada hari ketujuh, air mulai turun sedikit demi sedikit. Mungkin karena amarahnya sudah mulai mereda. Atau mungkin karena memang sudah cukup merusak.
Banjir meninggalkan lumpur dan sunyi.
Rumah-rumah berubah menjadi rangka kayu yang bisu. Dinding runtuh, lantai tertutup lumpur tebal, dan barang-barang yang dulu akrab kini tergeletak tanpa arti. Foto keluarga menempel di tembok dengan wajah yang nyaris tak terlihat. Halaman menjadi kubangan, dan jalan tak lagi bisa dibedakan dari sungai.
Ada yang kehilangan rumah.
Ada yang kehilangan pekerjaan.
Dan ada pula yang kehilangan seseorang tanpa sempat berpamitan.
Di tenda pengungsian, kehidupan berjalan dengan ritme yang sama sekali baru. Makan dari bantuan, antre air bersih, dan tidur di bawah terpal yang tak sepenuhnya menahan dingin malam. Wajah-wajah lelah terlihat di mana-mana. Beberapa mencoba tersenyum, beberapa lainnya hanya diam menatap kosong.
Malam terasa lebih panjang. Bukan karena gelap, tapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Ada rasa takut setiap kali hujan turun lagi, meski hanya rintik. Ada kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya terasa sesak di dada.
Di salah satu malam sunyi itu, seseorang berbisik lirih. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan di atas terpal.
“Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita…”
“Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita.”
Tak ada yang menimpali. Tapi banyak yang mengangguk pelan. Kalimat itu terasa dekat. Terlalu dekat. Seolah menggambarkan semua yang mereka rasakan, tanpa perlu penjelasan panjang.
Ini bukan kehidupan yang mereka inginkan.
Namun ini kehidupan yang harus mereka jalani.
Hari-hari berikutnya diisi dengan membersihkan sisa-sisa lumpur. Mereka kembali ke rumah yang sudah tak sepenuhnya bisa disebut rumah. Menyusun ulang apa yang masih bisa diselamatkan, meski jumlahnya sedikit. Kasur dijemur di bawah matahari, pakaian dicuci berulang kali, dan lantai disapu meski lumpur seakan tak pernah habis.
Anak-anak belajar tersenyum di tengah keterbatasan. Mereka bermain dengan apa saja yang tersisa hanya potongan kayu, botol plastik, atau sekadar berlari di tanah yang mulai mengering. Tawa mereka terdengar asing, tapi juga menguatkan. Seolah mereka mengingatkan bahwa hidup masih ada.
Para orang tua menyimpan duka mereka rapat-rapat. Tidak banyak cerita, tidak banyak keluhan. Mereka bangkit karena menyerah bukan pilihan. Setiap pagi, mereka menyapu lumpur yang tak kunjung habis, seakan sedang membersihkan luka yang sebenarnya belum sembuh.
Hujan memang belum sepenuhnya berhenti. Kadang turun lagi, membawa ingatan pada malam yang ingin dilupakan. Jantung berdebar setiap kali air sungai naik sedikit. Namun di sela derasnya, ada tangan yang saling menggenggam. Tetangga yang dulu hanya bertegur sapa, kini saling membantu tanpa diminta.
Ada doa yang terus dipanjatkan, dengan suara pelan tapi penuh harap. Ada keyakinan kecil yang perlahan tumbuh. Meski hidup tak lagi sama, mereka masih bisa melanjutkan langkah.
Mereka belajar bertahan bukan karena ingin, melainkan karena harus.
Dan mungkin, di situlah kekuatan itu tinggal.
Pada mereka yang tak memilih bencana, namun tetap memilih untuk hidup.
Para orang tua menyimpan duka mereka rapat-rapat. Tidak banyak cerita, tidak banyak keluhan. Mereka bangkit karena menyerah bukan pilihan. Setiap pagi, mereka menyapu lumpur yang tak kunjung habis, seakan sedang membersihkan luka yang sebenarnya belum sembuh.
Hujan memang belum sepenuhnya berhenti. Kadang turun lagi, membawa ingatan pada malam yang ingin dilupakan. Jantung berdebar setiap kali air sungai naik sedikit saja. Tapi di sela derasnya, ada tangan yang saling menggenggam. Tetangga yang dulu hanya bertegur sapa, kini saling membantu tanpa diminta.
Ada doa yang terus dipanjatkan, dengan suara pelan tapi penuh harap. Doa-doa yang mungkin tak lagi panjang, tak lagi indah susunannya, tapi lahir dari hati yang benar-benar lelah. Doa yang diucapkan sambil menyapu lumpur, sambil memeluk anak yang ketakutan, atau sambil menatap rumah yang tinggal separuh berdiri. Doa yang hanya berisi satu permintaan sederhana: ‘agar hari esok tidak lebih buruk dari hari ini.’
Ada bantuan yang datang, tak selalu dalam jumlah besar, tapi cukup untuk membuat mereka bertahan. Sekarung beras, sehelai selimut, sepiring makanan hangat dan hal-hal kecil yang tiba-tiba terasa sangat berarti. Ada orang-orang asing yang peduli, datang tanpa banyak bertanya, tanpa ingin dikenal namanya. Mereka membantu membersihkan lumpur, membagikan makanan, atau sekadar duduk menemani dalam diam. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa di tengah kehilangan, masih ada kemanusiaan yang tersisa.
Dari situlah keyakinan kecil itu pelan-pelan tumbuh. Keyakinan yang awalnya rapuh, sering goyah, tapi perlahan menguat. Bahwa mungkin, setelah semua ini, masih ada hari yang lebih baik. Bahwa meski rumah runtuh, hidup belum sepenuhnya selesai. Bahwa luka, seberat apa pun, suatu hari akan menemukan caranya sendiri untuk mengering.
Mereka belajar bertahan bukan karena ingin, melainkan karena harus. Setiap pagi mereka bangun dengan tubuh lelah dan hati yang belum sepenuhnya pulih, namun tetap melangkah. Dari reruntuhan, mereka belajar bahwa hidup tak selalu memberi pilihan. Kadang, hidup hanya memberi ujian, lalu menunggu siapa yang tetap berdiri, walaupun dengan lutut gemetar dan napas tertahan.
Tak semua dari mereka kuat setiap saat. Ada hari-hari ketika kesedihan datang tanpa izin. Ada malam-malam ketika air mata jatuh diam-diam, tanpa suara. Namun mereka terus berjalan, satu hari ke hari berikutnya, karena berhenti berarti tenggelam dalam kehilangan yang tak berujung.
Dan mungkin, disitulah kekuatan itu tinggal. Bukan pada mereka yang tak pernah jatuh, tapi pada mereka yang jatuh lalu memilih bangkit. Pada mereka yang tak memilih bencana, namun tetap memilih untuk hidup. Memilih bertahan, memilih berharap, dan memilih percaya bahwa dibalik semua yang hancur, masih ada alasan untuk melanjutkan langkah, meski pelan, meski tertatih, namun tetap maju.
Penulis bernama Musfirah, Mahasiswi Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala.
Editor: Khalisha Munabirah