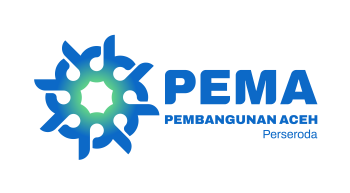Opini | DETaK
Dalam hukum pidana, mens rea adalah niat batin unsur subjektif yang menentukan apakah seseorang benar-benar bermaksud melakukan kejahatan atau sekadar menggunakan haknya sebagai warga negara. Tanpa mens rea, hukum kehilangan akal sehatnya. Tanpa akal sehat, hukum berubah menjadi alat kekuasaan. Dan di titik inilah kasus dugaan penghasutan publik terhadap komika Panji Pragiwaksono layak dibaca, bukan hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi sebagai cermin relasi yang kian tegang antara kritik, kekuasaan, dan paranoia negara.
Panji bukan politisi, bukan aktivis partai, dan bukan pejabat publik. Ia seorang komika. Namun di Indonesia, menjadi komika yang berbicara terlalu jujur sering kali lebih berbahaya daripada menjadi pejabat yang berbicara terlalu bohong. Ketika lelucon dianggap ancaman, kita patut bertanya, siapa yang sebenarnya rapuh; stabilitas negara, atau mental penguasanya?

Kasus ini muncul dari tuduhan bahwa pernyataan Panji dalam beberapa forum baik panggung stand-up, podcast, maupun media sosial—berpotensi menghasut publik dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Tuduhan yang terdengar berat, namun ironisnya ringan dalam pembuktian. Sebab yang dipersoalkan bukan tindakan konkret, melainkan tafsir atas kata-kata. Dan di negara yang konstitusinya menjamin kebebasan berekspresi, tafsir yang berlebihan adalah bentuk kemalasan intelektual aparat.
Dalam konteks mens rea, pertanyaan utamanya sederhana: apakah Panji memiliki niat jahat untuk menghasut publik melawan negara? Atau ia sekadar menjalankan fungsi kritik sosial yang secara historis justru menjadi penyeimbang kekuasaan?
Kritik Panji—sekeras apa pun nadanya—tidak pernah disertai ajakan kekerasan, pemberontakan, atau tindakan melawan hukum. Ia berbicara tentang kebijakan, tentang keganjilan logika negara, tentang absurditas pejabat. Jika itu disebut penghasutan, maka kita perlu kamus baru: kamus yang menempatkan kejujuran sebagai ancaman.
Masalahnya bukan pada Panji. Masalahnya ada pada negara yang alergi terhadap kritik, namun kebal terhadap rasa malu. Pemerintah yang mudah tersinggung oleh satire adalah pemerintah yang tidak yakin pada legitimasinya sendiri. Pemerintah yang kuat tidak sibuk membungkam suara, melainkan sibuk membenahi kebijakan.
Dalam sejarah demokrasi, satire selalu menjadi indikator kesehatan politik. Ketika satire hidup, demokrasi bernapas. Ketika satire dibungkam, demokrasi tercekik perlahan. Indonesia hari ini tampaknya memilih inhaler represif ketimbang terapi refleksi.
Menggunakan pasal penghasutan untuk menjerat kritik adalah praktik klasik negara otoriter yang sedang menyamar sebagai demokrasi. Pasal karet, tafsir lentur, dan aparat yang mudah tersinggung adalah kombinasi berbahaya. Ia menciptakan ketakutan, bukan ketertiban. Ia mendidik warga untuk diam, bukan berpikir.
Ironisnya, pemerintah sering kali berdalih bahwa kritik seperti Panji dapat “mempengaruhi opini publik secara negatif.” Pertanyaannya: sejak kapan opini publik adalah milik pemerintah? Bukankah publik berhak membentuk opininya sendiri, berdasarkan informasi dan pandangan yang beragam?
Jika opini publik mudah terhasut oleh satu komika, maka yang perlu dievaluasi bukan komikanya, melainkan kualitas komunikasi negara. Negara yang komunikasinya kuat tidak takut pada lelucon. Negara yang komunikasinya lemah akan menganggap setiap tawa sebagai ancaman.
Dalam kacamata hukum pidana modern, mens rea tidak bisa diasumsikan. Ia harus dibuktikan. Niat jahat tidak lahir dari kritik, melainkan dari dorongan merusak. Panji mengkritik untuk membuka diskusi, bukan menutup negara. Menyamakan kritik dengan penghasutan adalah bentuk kriminalisasi pikiran.
Lebih jauh, kasus ini menunjukkan pola berbahaya: pemerintah cenderung mempersonalisasi kritik. Kritik terhadap kebijakan dianggap serangan terhadap negara. Padahal negara bukan pejabat. Negara adalah rakyat. Dan Panji, suka atau tidak, adalah bagian dari rakyat itu sendiri.
Pemerintah yang anti-kritik sering kali berlindung di balik narasi stabilitas. Namun stabilitas tanpa kebebasan hanyalah ketenangan semu. Seperti air tenang di atas gunung api. Terlihat damai, tetapi menyimpan letupan.
Satire Panji justru berfungsi sebagai katup pengaman. Ia menertawakan kekuasaan agar kekuasaan tidak menertawakan rakyat. Namun ketika katup itu ditutup, tekanan akan mencari jalan lain. Dan sejarah menunjukkan, jalan lain itu jarang damai.
Ada kecenderungan berbahaya dalam birokrasi kita: menganggap kritik sebagai gangguan, bukan masukan. Ini mental feodal, bukan demokratis. Mental yang lebih nyaman dipuji daripada dikoreksi. Padahal negara bukan kerajaan, dan pejabat bukan raja.
Jika setiap kritik dianggap penghasutan, maka kita sedang menuju negara sunyi: sunyi dari perbedaan, sunyi dari diskusi, sunyi dari akal sehat. Yang tersisa hanya gema monolog kekuasaan.
Lebih lucu lagi atau tragis, pemerintah sering mengklaim terbuka terhadap kritik, tetapi hanya kritik yang sopan, lembut, dan tidak mengganggu tidur siang pejabat. Kritik yang terlalu tajam dianggap tidak etis. Padahal etika tanpa keberanian hanyalah dekorasi moral.
Dalam hukum, niat tidak bisa ditebak dari rasa tidak nyaman penguasa. Mens rea bukan soal perasaan tersinggung, tetapi soal maksud kriminal. Jika hukum digunakan untuk melindungi perasaan pejabat, maka hukum telah turun derajat menjadi perisai ego.
Kasus Panji seharusnya menjadi alarm. Bukan tentang siapa yang salah, tetapi tentang ke mana arah demokrasi ini berjalan. Apakah kita sedang membangun negara yang dewasa menghadapi kritik, atau negara yang mudah ngambek ketika ditertawakan?
Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan “apakah Panji bersalah?” melainkan “apakah negara masih waras?” Sebab negara yang sehat tidak takut pada komika. Negara yang sakit akan menganggap mikrofon sebagai senjata.
Jika mens rea diabaikan, hukum akan kehilangan rohnya. Dan ketika hukum kehilangan roh, yang tersisa hanyalah kekuasaan telanjang, dingin, kaku, dan tidak lucu sama sekali.
Mungkin inilah ironi terbesar: di negeri yang katanya demokratis, orang yang bercanda dianggap berbahaya, sementara yang korup sering kali hanya dianggap “oknum.” Jika ini bukan satire, maka kita benar-benar sedang hidup di dalam lelucon yang tidak lucu.
Dan ketika negara mulai takut ditertawakan, barangkali yang paling perlu dilakukan pemerintah bukan membungkam komika, melainkan bercermin dan belajar menertawakan dirinya sendiri. []
Penulis bernama Amanda Tasya, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Fathimah Az Zahra