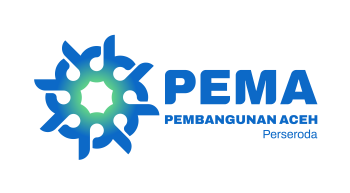Opini | DETaK
Di bawah langit kelabu dan di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat, terselip sebuah kisah usang yang tampaknya tidak akan memudar meski dimakan zaman. Kisah ini terus dirawat, diwariskan, hingga tumbuh subur dalam kehidupan. Ketika mendengar kata “patriarki”, apa yang pertama kali terlintas di benak saudara? Dominasi laki-laki dalam memimpin keluarga? Atau sesuatu yang kerap digaungkan para aktivis feminisme di media sosial?
Apa pun itu, patriarki telah mengakar kuat dalam budaya dan berperan besar dalam membentuk pola pikir masyarakat, termasuk dalam cara orang tua mendidik anak-anak mereka. Namun, yang menjadi pertanyaan yang sering terlintas, mengapa di banyak kasus, orang tua cenderung mempersiapkan anak laki-lakinya untuk menjadi “raja” dalam keluarga, sementara anak perempuannya dipersiapkan hanya untuk menjadi “pelayan” di rumah? Hanya sebuah pikiran, tidak ingin mengambil alih. Karena sadar akan kodrat yang telah tercipta, bukan juga sarkasme.

Tidak jarang dari kita mendengar stereotip tentang perempuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. “Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh, ujung-ujungnya di dapur, melahirkan anak, dan melayani suami,” ujar seseorang dengan angkuh. Atau, “Jangan kuliah terlalu tinggi, nanti tidak ada yang mau menikah denganmu,” tambah yang lain. Memang, menikah adalah jalan akhir dari kehidupan ini? Lebih menyedihkan lagi, kata-kata itu justru sering keluar dari mulut seorang perempuan yang juga memiliki anak perempuan. Seolah-olah telah tertanam dalam dirinya bahwa perempuan hanya diciptakan untuk mengurus rumah tangga, tanpa perlu menggali potensi atau mewujudkan impian mereka. Karena, sudah seperti itu kodratnya.
Padahal, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika perempuan tidak berpendidikan, bagaimana ia bisa mendidik generasi selanjutnya? Kita semua setuju bahwa anak yang cerdas lahir dari ibu yang cerdas pula. Lantas, mengapa kita masih meremehkan pendidikan bagi kaum perempuan? Menjadi ibu rumah tangga atau wanita karier adalah pilihan yang seharusnya bebas ditentukan oleh setiap perempuan, tanpa ada paksaan dan diskriminasi dari pihak manapun. Bahkan, mereka juga bisa menjalani keduanya. Betapa luar biasanya makhluk yang sering dianggap lemah ini.
Ketimpangan ini semakin terlihat ketika seorang anak laki-laki melakukan kesalahan fatal, tetapi orang tua dengan mudah memakluminya dengan alasan, “Namanya juga laki-laki, wajar saja.” Sebaliknya, ketika anak perempuan melakukan kesalahan serupa, mereka dikutuk, dicap buruk, dan dipandang sebelah mata. Dunia seolah begitu kejam terhadap perempuan yang melakukan kesalahan. Lantas, apakah seluruh dunia akan mengutuk perbuatan seorang perempuan hanya karena status gendernya? Mengapa perempuan hanya dijadikan sebagai “mesin pencetak anak,” tetapi suaranya tak pernah benar-benar didengar? Sejak dalam kandungan, perempuan kerap menjadi korban. Kehadirannya sering kali mengecewakan karena keluarga mengharapkan seorang “raja.” Sejak kecil, mereka dididik untuk mengalah, diajarkan pekerjaan rumah, dan dimarahi jika tidak sesuai harapan. Hidup mereka sudah diskenariokan untuk meneruskan kisah usang ini.
“Itu adalah kodrat perempuan, terima saja.” Jika benar demikian, untuk apa para pahlawan perempuan dahulu mati-matian memperjuangkan hak-hak mereka? Seolah dunia lupa bahwa tanpa perempuan, kehidupan tidak akan ada.
Lebih dari itu, perempuan juga kerap menjadi korban pelecehan, baik secara verbal maupun nonverbal, bahkan oleh sesama perempuan. Ironisnya, ketika mereka bersuara, justru mereka yang disalahkan, pakaiannya dikritik, perilakunya dihakimi. Tidak sekalian saja, kehidupannya yang harus disalahkan? “Salah sendiri terlahir sebagai perempuan.”
Salah satu contoh kecil yang sering kita temui adalah stigma terhadap tangisan. Dalam masyarakat, telah tertanam keyakinan bahwa hanya perempuan yang boleh menangis, sementara laki-laki yang menangis dianggap lemah dan dipertanyakan sisi maskulinitasnya. Padahal, menangis adalah fitrah manusia, terlepas dari gendernya.
Tulisan ini bukan untuk memerangi laki-laki. Sebab, mereka pun terkadang menjadi korban dari sistem ini. Mereka dipaksa untuk diam, menekan emosi mereka, menjadi “boneka raja” dalam harapan orang tuanya. Ah, ketika mereka berani berbicara, mereka justru dianggap tidak “jantan” atau disindir dengan kalimat, “Itu saja mengeluh, malu dong.”
Sampai kapan kita akan terus hidup dalam kisah usang ini? Sampai kapan perempuan harus terus mengalah dan laki-laki harus terus menekan perasaan mereka demi memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat? Sudah saatnya kita mempertanyakan dan menggugat sistem yang selama ini mengatur bagaimana perempuan dan laki-laki “seharusnya” hidup. Sebab, manusia bukan hanya tentang kodrat, tetapi juga tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Semua anak istimewa, terlepas dari apapun gendernya.
Penulis bernama Zikni Anggela, mahasiswi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor : Zarifah Amalia