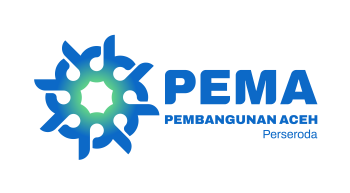Resensi | DETaK
Judul : Dari Pulau Buru Sampai ke Mekkah: Sebuah Catatan Tragedi 1965
Penulis : H. Suparman

Penerbit : Nuansa
Jumlah hlm : 343 halaman
Tahun terbit : September 2006
ISBN : 979-24-5628-7
Neo-kolonialisme, mungkin adalah kata yang sangat jarang kita dengar. Akan tetapi, secara tidak sadar, praktik kata tersebut telah lama ada dan menjadi bagian dalam keseharian kita. Contohnya saja kasus-kasus saat pemira tahun lalu. Sebagian kita tentu banyak mendengar atau bahkan mengalami secara langsung bagaimana sistem e-voting yang dipakai dalam pemira tahun lalu telah “menjajah” hak suara sebagian mahasiswa. Itu adalah contoh neo-kolonialisme yang ketahuan, lalu bagaimana dengan bentuk “jajahan-jajahan” lain yang tidak kita sadari? Dan bagaimana pula dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak menuntut hak mereka yang padahal telah dirampas? Kurang tepat rasanya jika kita menyalahkan mereka dengan alasan sikap skeptis yang mereka miliki. Bukankah sikap skeptis merupakan salah satu respon karena telah sering merasa dirampas?
Benar kata Bung Karno, bahwa rakyat Indonesia mesti waspada terhadap apa yang beliau katakan sebagai musuh pokok revolusi Indonesia, yaitu neo-kolonialisme. Nah, neo-kolonialisme inilah yang berkali-kali disuratkan dalam buku “Dari Pulau Buru Sampai ke Mekkah: Sebuah Catatan Tragedi 1965” yang ditulis oleh Suparman, mantan tapol (tahanan politik) G-30-S/PKI. Yang oleh Suparman, kata “neo-kolonialisme” dianggap sebagai personifikasi dari kekejaman rezim Soeharto.
“Mereka semua dianggap sebagai anjing kurap atau anjing buduk yang sangat menjijikan, yang sudah tidak pantas dipelihara dan diberi hak hidup lagi”. Seperti yang saya katakan sebelumnya, buku ini menceritakan tentang kehidupan seorang tapol yang sebelumnya adalah seorang wartawan senior, yang pernah keluar masuk istana negara, yang pernah bergaul dengan elit politik di zamannya, yang memiliki masa-masa kejayaan di dunia wartawan. Kejadian di ‘65, merubah total nasib pria tersebut. Menjadi seorang kuli yang hina-dina, dicampakkan dari bui satu ke bui lainnya, hingga dibuang ke sebuah pulau yang sunyi dan tandus. “Sebagai kuli cangkul atau kuli bangunan, atau kuli petik daun kayu putih dan kuli penebang dan penggergaji kayu, atau bahkan sebagai tukang kebun dengan pakaian compang-camping, merangkak-rangkak di bawah kaki seorang nona manis ‘gula-gula’-nya Komandan Inrehab” begitulah yang diceritakan pria tersebut.
Puncak dari penyiksaannya mungkin adalah berada di pulau Buru. Pulau tandus yang dikelilingi lautan Banda yang dalam dan dipagari hutan-hutan bakau yang menyesatkan. Bertahun-tahun terbuang di pulau Buru yang gersang sampai membuat Suparman dan tapol-tapol lainnya merasa “Pulau Buru sebagai tempat kelahiran kedua”. Pulau Buru telah menumbuhkan sikap solidaritas sesama tapol yang kuat melebihi sanak keluarga, tetapi juga para tapol yang “9 tahun dikerjapaksakan telah membangun pulau buru dari padang ilalang dan bukit-bukit gersang menjadi gudang padi Maluku.”
Ada satu hal yang saya rasa sangat unik dari seorang Suparman, itu adalah sikap realitis dan sikap tidak ingin berekspektasinya. Panta rhai yang artinya biarlah nasib berjalan seperti sungai atau conditio sine qua non yang artinya mau tidak mau harus diterima. Adalah jargon yang sering kali dipakai Suparman dalam bukunya. Jargon tersebut cukup untuk mewakili sebetapa pahit pengalaman hidupnya selama di cap sebagai tapol. Seakan ia tak akan kaget lagi bila ada nasib buruk yang datang kepadanya. Karena satu hal, Suparman percaya pada blessing in disguise atau berkah di dalam musibah. Seperti kata Suparman, “Pada mulanya hukuman-hukuman itu sangat menyedihkan, bukan hanya di badan, tapi juga di hati. Tapi lama-lama kami jadi kebal juga. Bahkan jadi guyonan, jadi bahan tertawaan. Kami menertawakan diri sendiri.”
Kekejaman neo-kolonialisme yang dirasakan Suparman berawal dari “Sesudah orang-orang komunis habis ditangkap dan dibunuh tanpa proses pengadilan, kini orang-orang Soekarno dan pecinta demokrasi lainnya yang mendapat giliran dijebloskan ke dalam penjara”. Beberapa kali diwawancara, hasilnya memang Suparman tidak terbukti bersalah. Tetapi karena ia sudah di cap sebagai tahanan politik, sehingga nasib dan kebebasannya pun bergantung pada keadaan politik yang ada. Tidak hanya luka secara emosional, tetapi juga cacat secara sosial dan politik. Seperti kata anak dan keluarga tapol, “Bagaikan anjing borok yang setiap saat bisa diusir dan dihardik”. Hidup dengan kekejaman rezim Sorharto tidak hanya menyiksa para tapol, tetapi juga para keluarga dan lingkungan tapol. Satu hal lagi yang unik dari Suparman, adalah ia tidak pernah memiliki dendam atau perasaan sentimental terhadap apa yang telah menimpanya.
Seperti yang saya katakana sebelumnya, Soeparman seakan tidak memiliki dendam terhadap apa yang telah terjadi. Bahkan juga tapol-tapol yang lainnya. Di pulau buru mereka seakan menemukan hiburan tersendiri, mendapatkan kehidupan yang baru, meskipun masih dalam status orang-orang “buangan”. “Ada yang tenggelam dalam ternak ayam, ada yang tenggelam dalam rawa-rawa pemancingan, ada yang tenggelam dalam Gedung kesenian”. Mereka sudah siap apabila pulau Buru jadi tanah kematian.
Saya kurang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Acep Zamzam Noor yang memberikan kata pengantarnya dalam buku tersebut, bahwa membaca buku “Dari Pulau Buru Sampai ke Mekkah: Sebuah Catatan Tragedi 1965” ini, baginya berasa seperti membaca sebuah novel. Bagi saya, membaca buku tersebut seakan saya bertemu dan mendengar langsung seorang Suparman bercerita tentang pengalaman hidupnya. Ada beberapa bagian yang seakan menghidupkan buku tersebut “berubah menjadi penulisnya, Suparman”. Sehingga ketika membacanya, saya seakan mendengar secara langsung seorang Suparman bercerita. Terlepas dari itu, Ada juga hal yang saya sependapat dengan pelukis dan sastrawan peraih SEA Write Award tersebut, bahwa buku Suparman ini memiliki tulisan yang puitis dan juga mengandung bobot sastra.
Kepada siapapun yang masih latah, ikut-ikutan menuduh orang-orang yang tak berdosa sebagai biang keladi dari segala peristiwa, atau siapapun yang tertarik dengan isu-isu G-30-S, atau siapapun yang merasa sebagai communist phobi, atau yang hanya mengenal G-30-S dari film Pengkhianatan G 30-S/PKI karya Arifin C. Noer yang biasa rutin diputar pada malam 30 September. Saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku “Dari Pulau Buru Sampai ke Mekkah: Sebuah Catatan Tragedi 1965” karya Suparman ini. Karena dari buku ini, kita akan menemukan satu sisi yang sering disembunyikan atau tidak pernah kita ketahui sebelumnya.
Penulis bernama Ahlul Aqdi, mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala. Ia juga merupakan anggota aktif di UKM Pers DETaK USK.
Editor: Della Novia Sandra