
SEPERTI MAKAN, TOLERANSI ADALAH SUATU KEHARUSAN, KEBIASAAN, BAHKAN MUNGKIN ALAMIAH DALAM KEHIDUPAN UMAT YANG BHINNEKA. ITULAH SALATIGA. DAN BEGITULAH INDONESIA SEMESTINYA. (DANIEL HERRY ISWANTO)
Travel Journalism – Beberapa waktu lalu media massa Indonesia dipenuhi dengan berita kekerasan atas nama agama seperti Tolikara, Aceh Singkil, Gafatar dan terakhir perusakan Vihara oleh sekelompok orang di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sebagaimana kasus-kasus serupa, hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) terhadap kasus Tanjung Balai menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi karena distorsi informasi yang disebarkan oknum tertentu.
Seperti dikutip dari situs resmi Komnas HAM, beredar isu bahwa seorang warga etnis Tionghoa melarang adzan dan mematikan pengeras suara masjid. Padahal yang terjadi hanyalah penyampaian keberatan mengenai suara adzan dari Masjid Al-Makshum, Tanjung Balai oleh seorang warga Tionghoa kepada tetangganya. Keberatan itu pun disampaikan kepada pihak Masjid Al-Makshum dengan harapan bisa diteruskan ke pengurus masjid. Sempat terjadi dialog dan mediasi bahkan yang bersangkutan sudah meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut.
Di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik-konflik yang disebut di atas hanyalah segelintir dari berbagai kasus keberagaman yang memanas di Indonesia. Kemajemukan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang merupakan kebanggaan bangsa ini tidak jarang menjadi awal mula konflik. Ibarat jerami kering disulut percikan api, isu SARA dalam dua dekade terakhir justru sangat sensitif di kalangan masyarakat Indonesia.

Pemandangan berbeda tampak dalam kehidupan keberagaman Salatiga. Pilar bangsa Bhinneka Tunggal Ika saat ini tercermin dalam keseharian kota yang bersemboyan Hati Beriman.
Kota Salatiga dengan komposisi Muslim sebagai mayoritas tampak berjiwa besar dengan bertoleran terhadap perbedaan agama. Jika kita mengunjungi Lapangan Pancasila, alun-alun Kota Salatiga, terdapat satu masjid dan empat gereja. Tak begitu jauh dari Lapangan Pancasila, terdapat Klenteng Hok Tek Bio yang menjadi pusat keagamaan etnis Tionghoa di Salatiga.
Pendeta Daniel Herry Iswanto, salah satu pendiri dari Majelis Pimpinan Umat Agama Salatiga (Majelis PUASA), siang itu, Sabtu, 3/9/2016, mengatakan bahwa, “Dari elit hingga akar rumput umat beragama, kami semua bertoleransi. Tidak hanya tokoh-tokoh agamanya saja.”
Di salah satu ruang pertemuan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Salatiga, Daniel bercerita bahwa komunitas umat agama seringkali mengadakan diskusi perihal toleransi dan kerukunan umat beragama. Kegiatan tersebut diadakan bergantian di rumah-rumah ibadah yang berbeda setiap bulannya.
Komunitas serupa, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Komunitas Keluarga Sehat Insani (Kehati) juga seringkali mengadakan berbagai kegiatan bersama. Olahraga, mengadakan pasar murah, menanam pohon, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, dan aksi-aksi sosial lainnya menjadi perekat-perekat kecil yang menyatukan Salatiga.
Daniel, yang merupakan Pendeta GKJTU, lebih jauh menuturkan bahwa tidak sekadar di tingkat elit agama, geliat pemuda pun tak mau ketinggalan mendorong keberagaman menjadi nafas sehari-hari Salatiga. Mereka yang tergabung dalam komunitas Sobat Muda dan Wacana Lintas Iman sering menggelar diskusi-diskusi dan pembuatan film seputar isu keberagaman yang menjadi pemantik api semangat bertoleransi. Camping atau retreat antar-iman kerap digelar Sobat Muda untuk menumbuhkan semangat kebersamaan.
“Ibu dari istri saya seorang muslim, keluarga saya sendiri tidak semua Kristen,” ujar Daniel seakan ingin menekankan bahwa di Salatiga keberagaman memeluk agama sangat dihormati bahkan di tingkat yang paling kecil dan sederhana: keluarga.
Bambang, seorang pesepeda berusia 67 tahun, begitu bersemangat ketika bercerita soal toleransi yang di wilayah yang dikenal sebagai Kota Pensiun ini.
“Kalau di Lapangan Pancasila ini, sering untuk doa bersama, ya Khonghucu, Kristen, Hindu, Budha dan Islam. Kami doa bersama di satu tempat,” ucap Bambang. Pemeluk Kristen Protestan yang sejak lahir tinggal di Salatiga ini menunjuk ke arah jalan di sekitar lapangan dan berkata bahwa jalanan tersebut setiap kali digelar doa bersama penuh oleh masyarakat yang bersatu dalam perbedaan.
Masih di sudut lain dari Lapangan Pancasila yang teduh, cerita Sumarto seorang penjual kacang rebus menjadi ketok palu bahwa Salatiga memang patut disebut kota toleran. Di usianya yang menginjak 105 tahun, Sumarto mengingat kembali ketika ia pertama kali berjumpa dengan seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya.
“Namanya ….. ya, istri saya Tionghoa,” tutur Sumarto dengan bibir sedikit gemetar sehingga kurang jelas ia menyebut nama juwita pujaannya itu.
Sumarto sendiri berasal dari suku Jawa yang sejak kecil tinggal di Salatiga. Baginya, pernikahan beda etnis dan keluarga berbeda agama sudah ada sejak dulu dan itu merupakan hal yang biasa.
“Sudah sejak zaman Wihelmina (Hindia Belanda -red), iya,” ungkap Sumarto yakin.
Bagi Sumarto, Bambang dan Pendeta Daniel, barangkali kata toleransi bukanlah suatu hal yang sepesial. Seperti makan, toleransi adalah suatu keharusan, kebiasaan, bahkan mungkin alamiah dalam kehidupan umat yang bhinneka. Ketika umat Islam beribadah di lapangan kota, seperti Salat Idul Fitri dan lainnya, pemuda agama lain turut membantu melancarkan prosesi dan begitupun sebaliknya.
Kedamaian antariman Salatiga sayangnya tidak banyak mendapat perhatian dari media massa. Padahal, promosi keharmonisan dalam keberagaman kota kecil ini bisa menjadi salah satu wilayah yang menginspirasi daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Perlukah Indonesia menciptakan Salatiga-Salatiga lain, menghadirkan keharmonisan-keharmonisan yang mendamaikan di daerah lainnya? Dengan terus meningkatnya intoleransi dan diskriminasi di Indonesia, maka mendorong dan menciptakan toleransi-toleransi bagi Tanjung Balai, Aceh Singkil, Tolikara dan daerah-daerah lainnya adalah suatu keharusan.
Jadi, kesimpulan dari potongan cerita Sumarto, Daniel, dan Bambang tentang Salatiga: Toleransi seperti keharusan bagi setiap orang layaknya makan untuk melangsungkan kehidupan.
**Tulisan ini buah Workshop Pers Mahasiswa SEJUK dan kunjungan peserta ke Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Salatiga yang dilaporkan Vanda Dwi Septika Situmeang (Suara Mahasiswa, Universitas Indonesia), Maida Yusri (Ganto, Universitas Negeri Padang), Riska Iwantoni (DETaK, Unsyiah, Aceh), Andri Setiawan (Lentera, UKSW Salatiga), Nurcholis Ma’arif (Himmah, UII Yogyakarta), Anggino Tambunan (Suara Mahasiswa, Universitas Indonesia).
***Workshop ini terselenggara berkat dukungan penuh Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) yang bekerjasama dengan SEJUK, LPM Lentera UKSW Salatiga dan The Asia Foundation.
Sumber: SEJUK

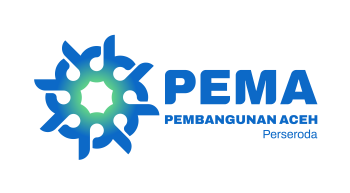
![[LENSA] Fasilitas USK yang Direnovasi Pasca PON](https://detakusk.com/wp-content/uploads/2024/09/detak-lensa1-238x178.jpg)








