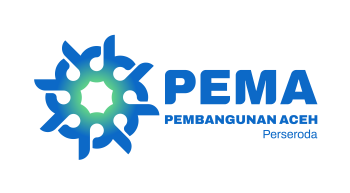Oleh Yelsa Yusuf

Setiap kali aku memandang pajangan foto di balik lemari baju, aku teringat Ibu. Aku hanya tahu wajahnya melalui foto itu, hanya foto itu. Ibu tak hanya meniggalkanku, tapi juga ayah. Ternyata senyum manis foto kusam itu hanya bertahan setahun, setelah hadirnya diriku, maka pergilah Ibuku dijemput Sang khalik, tapi setidaknya dengan lembaran foto ini, aku mengetahui sekilas wajah ibuku.
Ontel tua penuh karat ini selalu jadi kendaraan kebanggan kami. Ayah selalu mengayuhnya dengan penuh semangat, meski harus terengah-engah. Kulihat anak lainnya diantar menggunakan mobil, mereka tak perlu menghirup debu yang beterbangan di jalan, mereka hanya perlu duduk manis di dalamnya, hingga sampai ke sekolah. Sepatu mereka pun selalu terlihat bersih. Tak seperti sepatuku, kumal dan penuh jahitan.

“Yah, enak ya kalau bisa naik mobil,” kuutarakan kata hatiku pada ayah sambil menarik bajunya.
“Siapa bilang? Enakan naik sepeda lagilah nak, sehat dan terhindar dari macet.” Jawab ayah.
Ayah hanyalah juru parkir, seusai menjemputku di sekolah, ia bekerja hingga sore dan malamnya ia bertugas membersihkan masjid yang letaknya di samping tempat parkir ayah bekerja. Susana rumah yang selalu sepi membuat hubungan aku dan ayah tak selamanya harmonis.
“Yah! Sepatu Saleh sudah koyak,” aku mengeluh dengan suara yang sedikit keras. Ayah menatap sepatuku dengan perlahan. Ia tahu sepatu itu layakanya mulut unta yang menganga kehausan. Iya Nak, nanti ayah belikan sepatu baru. Aku tau, itu janji palsu, untuk mengenyangkan pintaku.
“Iya iya saja, entah kapan dibelikan.” Dengan kesal aku masuk dan membanting pintu kamar dengan keras.
Rumah kumuh yang menjadi istana kami semalam telah habis dilalap api, sebab lampu capluk jatuh saat angin berhembus kencang, hingga melalap habis dinding-dinding dan melalap satu-satunya gorden yang menjadi pengganti jendela kamar kami, hanya tersisa pintu kamar yang menjadi saksi amukanku pada ayah semalam, dengan menyesal aku memeluk ayah dengan erat.
Sambil mengelus ubun ku, ayah berkata “Sudahlah jangan menangis, beruntung kita bias selamat.” Aku pun hanya bias menangis, itulah yang bias kulakukan saa tini.
Aku berhenti sekolah, sebab ayah sudah tak mampu membiayai segalanya. Keriput yang membingkai di wajahnya, seolah menandakan betapa tuanya wajah ayahku dari umurnya. Aku membantu ayah merapikan jajaran sepeda motor yang ada di parkiran. Malamnya aku membantu ayah membersihkan masjid, rutinitas ini terus kami lakukan, hingga ayah jatuh sakit. Aku yang menggantikan posisi ayah saat ia sedang sakit, agar posisi ayah tidak digantikan dengan orang lain, sementara ayah kutitipkan di rumah rumah tetangga.
Kusempatkan menghabiskan sisa malamku untuk menunaikan salat wajib, lalu aku berdoa sambil menangis, “Sekiranya boleh memilih, aku tidak ingin dilahirkan seperti ini Tuhan, hidup dalam kemelaratan, untuk apa hidup jika hanya menjadi kesusahan bagi Ibu dan Ayahku, demi aku Ibu rela mempertaruhkan nyawanya, demi aku ayah rela bekerja seharian, sampai jatuh sakit dan karena aku rumahku habis terbakar.
Mungkinkah aku pembawa kesialan bagi mereka Tuhan? Bahkan untuk membeli sepatu pun tak mampu, apa lagi melanjutkan sekolah, aku lelah Tuhan cabut saja nyawaku jika memang itu jalan kebahagiaannya.” “Aamiin”. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, kuhapus linangan air mata yang tersisa, aku segera pulang menemui ayah.
“Leh, Saleeeh!!! Saleeh” Terdengar teriakan panjanglaki-laki dari jauh memanggil namaku. Ada apa bang Fajar?” Tanyaku heran. Dengan napas yang terengah-engah ia menjawab, “Ayahmu, Ayahmu ditabrak mobil di pasar, Leh.”
Tanpa pikir panjang kutinggalkan pelataran parkir, kukayuh sepeda ontel ayah dengan cepat, tak peduli makian orang-orang, karena aku mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan. Sesampainya di sana, ternyata ayah tidak ada, hanya ada sisa darah segar yang berceceran di aspal, aku bingung.
Ternyata ayah telah dibawa ke rumah sakit. Ku kayuh lagi sepeda dengan cepat, hingga ban sepeda bocor pun tak kupedulikan. Ku kayuh terus hingga ban sepedaku bocor dua-duanya.
Akhirnya kutinggalkan sepeda di pinggir jalan. Sambil menangis, aku pun berlari dengan sekencang-kencangnya berharap segera sampai menuju sumah sakit yang letaknya berseberangan dengan kantor pos. Mukaku memerah, napasku terengah-engah keringatpun mengalir deras.
Ayah telah tiada, ia meninggal saat akan dibawa ke rumah sakit. Seorang perawat pun memberikan sebuah kado padaku, katanya kado itu ada dalam genggaman ayah, ternyata ayah memaksakan dirinya ke toko untuk membelikan sepatu, demi menepati janjinya. Tangisanku semakin menggila, sebagian pegunjung hanya mengasihaniku.
Hari terus berlalu. Kehidupanku tak berubah. Di Masjid ini, kembali aku bermunajat, aku menangis sejadi-jadinya, sampai mengeluarkan cairan merah dari hidungku. “Tuhan, mengapa tega betul kau mengambil mereka, mengapa bukan aku saja.” Mengapa tega menjadikan aku yatim piatu. Kini aku sendiri, doaku tak karuan karena dikuasai ego.
Sambil memeluk sepatu, aku terlelap dalam buaian tangisanku, di atas sajadah aku bermimpi bertemu Ayah dan Ibu, aku pergi menyambut lambaian tangan mereka. Semoga ini bukan mimpi.[]
Penulis bernama lengkap Elsa Jahra Yusuf, ia juga mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia FKIP Unsyiah angkatan 2012. Dara kelahiran Kuala Simpang 12 Juli 1994 ini sekarang menetap di Banda Aceh.
Editor: M Fajarli Iqbal