Cerpen | DETaK
Nafasnya terengah-engah, tubuh tambun itu dia sandarkan ke bongkahan batu besar dibelakangnya. Tangannya bergerak asal, mencoba meraih botol minum yang seingatnya ia taruh dibawah kaki. Namun nihil, dia tidak menemukan letak botol minum itu. Dengan tenaga yang tersisa, Adi berusaha berdiri tegap dan melihat sekeliling, hanya ada bongkahan batu dibawah kakinya.
Ia melihat ke kanan dan kiri, pemandangan masih sama walau sedikit samar karena banyaknya debu yang terbawa angin. Matanya kini menoleh ke arah kaki gunung, dan benar saja, botol minumnya ada disana, menggelinding dengan cepat hingga tak terlihat lagi.

Adi menghela napas panjang, menyerah dengan kondisinya yang harus kehausan sampai pekerjaannya selesai. Pak Yono yang terus berteriak di seberang sana pasti akan memarahinya jika ia tahu salah satu pekerjanya keluar dari area bekerja tanpa membawa bongkahan batu yang ia minta.
Adi pun kembali ke posisi semula, bersandar di bongkahan batu yang seharusnya ia pecahkan. Tubuhnya terlalu lelah dan haus untuk kembali bekerja. Adi memandangi kedua tangannya yang penuh luka lecet. Hari ini ia lupa membawa sarung tangan yang biasa ia pakai untuk melindungi tangannya selama memegang martil yang ia gunakan untuk membelah batu. Kayu pegangan martilnya sudah lapuk, sehingga ada serat-serat kayu tajam yang mencuat disana-sini.
Adi mengaduh, menyangga tubuh dengan tangannya saja ia sudah tak mampu. Panas terik hari ini membuat bongkahan batu yang ia sandari menjadi panas, rasa sakit yang ia rasakan semakin menjadi-jadi apabila ia menempel tangannya disana.
“ADI!”
Sial, dia ketahuan. Adi memperbaiki posisi menjadi berdiri tegap, di sebelahnya sudah terlihat Pak Yono yang melangkah mantap, menghampiri Adi dengan wajah penuh amarah. Pak Yono kini sudah berdiri di hadapan adi dengan tangan terlipat di atas perut buncitnya. Cincin-cincin emas besar yang melingkari setiap jarinya memantulkan cahaya matahari ke mata Adi, membuat pemuda itu memicingkan matanya.
“Kau ini ngapain sih?! Bukannya kerja malah santai-santai. Kau kira badan gendut kau bisa pecahkan batu-batu itu hah?!”
“Maaf pak.” Ujar Adi pelan.
“Maaf-maaf, Kerja kau!”
Pak Yono melenggang pergi, belum dua langkah ia pergi mulutnya sudah kembali berteriak ke pekerja lain. Adi enggan mendengar suara pak Yono lagi. Ia langsung kembali mengambil martil dan menghujamnya keras ke permukaan batu. Suara berisik martil dan bongkahan batu yang berjatuhan cukup untuk meredam suara pak Yono.
***
Adi jalan tertatih menyusuri jalan setapak yang dikelilingi semak belukar. Tangan penuh lukanya sibuk menghitung uang yang ia dapatkan sebagai upah. Akibat ketahuan beristirahat tadi, pak Yono memotong sebagian upah Adi. Jadi, uang yang didapatkan Adi kurang dari biasanya.
Hal itu membuatnya takut, ia tak berani pulang ke rumah membawa uang lebih sedikit. Upah biasa saja sudah sedikit apalagi upah yang dipotong. Tak terasa, Adi sudah sampai di ujung jalan setapak, tepat di depan rumahnya. Cahaya lampu temaran dari rumah menjadi tanda bahwa ayahnya sudah ada di rumah. Adi menelan ludah susah payah, tubuhnya sudah gemetar.
Pintu pun terbuka, tampak sosok ayahnya keluar dari rumah. Wajahnya yang selalu penuh amarah itu mengingatkan Adi dengan pak Yono, membuat pemuda berusia 16 tahun itu ketakutan. Di tangan si ayah sudah ada ember berisi air yang tanpa aba-aba langsung ia siram ke Adi.
“Sudah kukatakan berapa kali? Jangan kau tapakkan kakimu ke rumah dengan badan bau keringatmu itu!” Suara ayah menggelegar.
Adi menjawab sang ayah dengan anggukan, mulutnya tak sempat menjawab, ia sibuk menjilati tetesan air yang membasahi tubuhnya. Akhirnya ia bisa merasakan air setelah kehausan dari pagi hingga petang.
Si ayah menyodorkan tangannya, bermaksud untuk meminta upah hasil kerja Adi hari ini.
“Duit sini!”
Adi termangu, ia meremat uang itu digenggaman, terlalu takut untuk memberikannya kepada sang ayah. Tingkah Adi membuat ayahnya tak sabaran sehingga ia langsung menarik tangan Adi dan merebut uang tersebut. Tangannya langsung menghitung uang itu, tatapan matanya semakin menajam seiring lembaran uang itu usai ia hitung.
“Kenapa duitnya cuman segini?! Kau kemanakan duitnya hah?!” Seru sang ayah, ember yang ia pegang dilemparkan ke arah Adi yang sudah berlutut dan menangis.
“Maaf yah, aku tadi ketahuan istirahat sama pak Yono. Jadi, upahku dipotong setengah,” Adi berusaha menjelaskan diantara isak tangisnya.
Sang ayah yang semakin tersulut emosi meraih sendal dan melempar sendal itu ke arah Adi. “Emang nakal kau ya! Kalau lagi kerja tuh kerja! Tidur diluar kau hari ini! Kesal aku.”
Sang ayah melangkah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. Meninggalkan Adi yang masih tergeletak menangis dibawah langit yang semakin gelap.
***
Eko keluar dari dapur, tangannya membawa nampan berisi roti tawar dan kopi, sarapan kesukaan anaknya, Adi. Ada sedikit rasa bersalah di hati kecilnya karena menyuruh anak semata wayangnya itu untuk tidur diluar kemarin. Jadi, ia pikir membawa sarapan untuk si anak setidaknya bisa membuat rasa bersalahnya itu menghilang. Lagipula, ia hanya ingin anaknya itu menjadi kuat. Itu didikan yang tepat untuknya, menurut Eko. Setelah ditinggal oleh almarhumah sang istri, Eko membesarkan Adi seorang diri. Anak itu cengeng dan lemah lembut, persis seperti ibunya. Menurut Eko, pribadi seperti itu tak cocok untuk Adi bertahan hidup kedepan. Sehingga ia menerapkan didikan keras pada anaknya itu. Semua untuk masa depannya.
Eko membuka pintu, tapi, bukannya melihat tubuh besar Adi yang tertidur di depan pintu, ia malah mendapati teras yang kosong. Eko melihat ke segala arah, berusaha mencari dimana anaknya itu mungkin tertidur. Namun nihil, ia tidak melihat sosok Adi dimanapun. Eko melangkah menuju ke belakang rumah, tempat dimana kamar mandi sederhana mereka berada. Mungkin saja Adi disana, sedang mandi atau malah tidur untuk menghindari nyamuk. Tapi sama saja, Adi tidak ada.
Eko kembali ke depan rumah, matanya berjumpa dengan sosok nek Dwi, tetangganya. Wanita tua itu melempar senyum yang dibalas sekedarnya oleh Eko. Eko sudah duluan kesal dengan Adi, anak itu pasti berkeliaran, pikirnya. Ia meraih sapu lidi yang ia taruh di sisi rumah dan berniat langsung mencari anaknya itu untuk memberi sabetan sapu lidi.
“Mau kemana?” langkah Eko terhenti ketika nek Dwi tiba-tiba bersuara.
“Cari Adi.” Jawab Eko singkat dan kembali melangkah.
“Untuk apa kau bawa sapu lidi? Bocah batu itu butuh martil baru buat kerja bukan sapu lidi.”
Eko memalingkan pandangannya ke arah nek Dwi. Ia berjalan pelan menghampiri Eko dan merebut sapu lidi yang Eko bawa, senyum kembali terukir di wajahnya.
“Bocah batu itu pergi kerja pagi-pagi sekali. Dia nitip pesan ke aku buat ngasih tahu kau. Dia bilang, dia bakal lebih rajin kerja dan janji untuk bawa upah penuh hari ini.”
Eko terdiam. Nek Dwi kembali berjalan, kini ia bergerak ke arah rumah Eko. Tangan ringkih itu menaruh sapu lidi yang Eko bawa tadi ke tempat semula. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah plastik kusut dari kantung bajunya dan memasukkan roti tawar serta kopi yang Eko siapkan untuk Adi tadi kedalamnya. Wanita tua itu kembali menghampiri Eko dan menyodorkan roti dan kopi yang sudah ia bungkus.
“Ini, bawa ke tempat kerja anakmu. Kasihan dia belum makan apapun dari kemarin.”
Benar juga, Adi belum makan apapun kemarin, bahkan minum pun mungkin tidak. Biasanya Eko dan Adi makan hanya malam dan pagi saja. Namun, kemarin pagi Adi telat bangun sehingga Eko menghukum Adi dengan tidak memberinya sarapan. Dia juga menghukum Adi tidur di luar semalam dan tidak memberinya makan malam. Rasa bersalah Eko semakin besar. Ia mulai merasa bahwa ia terlalu keras dengan anaknya. Anaknya yang juga ikut lelah untuk mencari nafkah.
Nek Dwi menepuk pundak Eko. “Kau tahu nggak? Batu, kalau disiram air terus, dia bakal terkikis, terbelah, kemudian melebur menjadi abu dan terbang dibawa angin. Kau sudah kehilangan satu batu dalam hidupmu, jadi, jaga bocah batu itu baik-baik. Sayangi dia dan perlakukan dia seperti anak, anak-anak.”
Eko mengangguk. Ia paham pesan tersirat yang disampaikan nek Dwi. Akhirnya, ia berpamitan dengan nek Dwi dan segera melangkah dengan semangat menuju tempat kerja anaknya. Ia berjanji dalam hati, bahwa ia tidak akan menyiram bocah batunya lagi, sebaliknya ia akan memoles bocah batunya itu hingga ia menjadi berharga dimasa depan.
“Adi! Ayah bawakan sarapan!”
Penulis Bernama Rossdita Amallya, Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Syiah Kuala. Ia juga merupakan anggota aktif di UKM Pers DETaK.
Editor: Teuku Ichlas Arifin

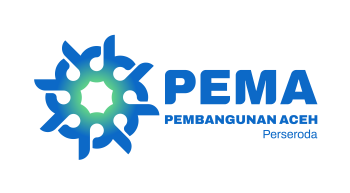


![Melodi Hujan di Bulan September Amirah Nurlija Zabrina [AM]](https://detakusk.com/wp-content/uploads/2024/09/ILUSTRASI-CERPEN-238x178.png)






![[Infografis] Profesor di USK dan Syarat Menjadi Profesor](https://detakusk.com/wp-content/uploads/2025/01/Profesor-USK-100x75.png)
