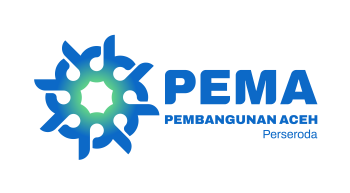Resensi | DETaK
Judul : Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi
Penulis : Syamsuddin Haris
Genre buku : Sejarah
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
ISBN : 978-979-461-881-3
Tebal halaman : 243
Ukuran Buku : 14,5 x 21 cm
Tahun Terbit : 2014
Buku ini ditulis oleh Syamsuddin Haris, seorang peneliti senior di Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Beliau menulis sejumlah buku, salah satu karyanya, Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman (1995) memperoleh penghargaan sebagai Buku Terbaik bidang Ilmu Sosial dari Yayasan Buku Utama pada 1996.

Buku “Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi” ini membahas mengenai awal terealisasikannya demokrasi di Indonesia secara tidak sempurna, dengan maksud ada masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan masa yang terjadi saat orde baru dan presiden yang memegang kekuasaan pada masa reformasi. Selain melihat masalah yang terjadi, buku ini juga memberi solusi dan bahan berpikir yang dapat dilakukan dan dipertimbangkan oleh pembaca. Berawal dari bab I dijelaskan mengenai demokrasi elektoral yang terjadi di Indonesia. Ketika dalam pemilihan diberikan kebebasan, demokrasi dan langsung, namun tata kelola pemerintahan semakin tidak meyakinkan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin tidak terkendali dari berbagai tingkat dan cabang di pemerintahan, eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif. Para elite bangsa seakan mati rasa, tidak adanya kepedulian dan tanggung jawab dalam mensejahterakan rakyat serta menyelamatkan bangsa.
Ada beberapa faktor yang menjadi akar masalah yang sedang dihadapi bangsa, salah satunya kegagalan konsolidasi kekuatan politik sipil pada momentum reformasi 1998-1999. Perlu dipahami bahwa beberapa faktor masalah tersebut merupakan hasil sistem politik otoriter di bawah Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998). Akibat dari sistem otoriter yang panjang tidak hanya memelembagakan saling curiga dan diskriminasi antar golongan tertentu, namun juga mewariskan pragmatisme politik yang dapat memberi dampak fatal bagi akal sehat, kecerdasan dan kreativitas bangsa. Maka dari itu, untuk memberi perubahan yang sesungguhnya pada bangsa adalah dengan saling percaya, kerja sama, dari berbagai elemen kekuatan civil society. Hal ini diperlukan untuk mendesak elite penyelenggara negara, yang paling bertanggung jawab terwujudnya perubahan bangsa. Terealisasinya demokrasi yang substansial, terkonsolidasi dan bermakna juga diperlukan warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawab atas nmmmmmpolitik dan ekonomi negeri.
Bab II membahas mengenai tata kelola negara yang masih jauh dari harapan. Setelah turunnya presiden Soeharto, Indonesia memiliki harapan untuk menjadi negara baru yang lebih adil, sejahtera dan demokratis. Namun, itu hanya menjadi retorika dan jargon para elite politik dan penyelenggara pemerintahan. Adanya ketimpangan dalam merawat dan mengelola negara, sehingga muncul rasa curiga dan saling tidak percaya antar masyarakat maupun antara masyarakat dan negara. Hal ini menyebabkan adanya konflik antar kelompok baik di pusat dan di daerah. Problematika yang terjadi, tidak terlepas dari perbedaan-pebedaan. Lahirnya Indonesia beserta rumusannya, juga berawal dari perbedaan-perbedaan dari para pejuang terdahulu. Hal tersebut dilalui sehingga terlahirlah pancasila sebagai ideologi bangsa dengan telah mewadahi segala kebutuhan bangsa dalam mempersatukan keberagaman.
Beralih ke era demokrasi, tantangan bagi negara lebih besar dibandingkan pemerintahan otoriter Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto. Hal ini dikarenakan demokrasi membuka peluang yang lebih besar bagi tegaknya politik identitas berbagai kelompok etnik, daerah, agama dan ideologi yang termarjinalkan atau terpinggirkan selama era otoriter. Demokrasi tidak hanya menguatkan bangsa, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan bangsa. Maka dari itu, perlu bagi penyelenggara pemerintah memiliki kemampuan mengelola keberagaman sebagai aset bangsa untuk membentuk rasa nasionalisme yang tentunya akan berkontribusi positif bagi masa depan bangsa.
Bab III, mengenai ploblem demokrasi presidensial Indonesia di bawah tiga orang presiden pasca Orde Baru, yakni Wahid, Megawati dan Yudhoyono. Selain itu juga, konstitusi yang berbeda, yakni UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Presiden pertama yang dipilih secara demokratis oleh MPR, ialah Abdurrahman Wahid. Konflik Presiden-DPR era Wahid mendorong keberhasilan amandemen UUD 1945. Adanya kelebihan dan kekurangan antara sistem presidensial dan parlemen, berdasarkan yang dipraktikkan di negara lain. Fluktuasi relasi Presiden-DPR tidak hanya disebabkan variabel institusional yang melekat pada presidensialisme, melainkan juga akibat supremasi DPR pasca-amandemen konstitusi di satu pihak. Maka dari itu, untuk menumbuhkan efektivitas pemerintah, perlu adanya penataan kembali yang lebih konstruktif dengan prinsif checks and balances. Baik melalui amandemen kembali konstitusi maupun rekayasa institusional yang bisa introdusi dalam undang-undang bidang politik.
Bab IV, membahas mengenai koalisi di bawah sistem presidensial dan pada pemerintahan Presiden Yudhoyono. Koalisi yang dibentuk pasca Orde Baru menjadi lebih beban ketimbang solusi agar terbentuknya pemerintahan yang efektif. Dalam sistem presidensial berbasis multipartai untuk membentuk pemerintah yang bisa memerintah diperlukan koalisis yang memiliki kesamaan ideologi dan arah politik yang satu. Hal tersebut dilakukan, dengan harapan dukungan ataupun penolakan terhadap suatu kebijakan berorientasi pada kepentingan bangsa buka kepentingan jangka pendek. Selain itu juga, agar relasi Presiden-DPR tidak hanya menjadi wadah transaksional politik antarpetinggi pemerintah dan politikus parpol di Senayan.
Presiden Yudhoyono harus menanggung beban atas pembentukan koalisinya yang semu, longgar dan tidak memiliki ideology yang sama yang menyebabkan kepemimpinan politik yang lembek dan tidak memiliki keberanian politik dalam berhadapan dengan parpol di DPR. Dan hal tersebut terjadi lagi pada periode kedua pemerintahan beliau. Karena itu, penataan ulang sedemikian rupa pun tidak menjamin kohesitas dan soliditas antara parpol koalisi. Dengan demikian, solusi yang dapat dilakukan untuk kedepannya dengan menata ulang format pemilu. Kedepannya hanya ada dua momentum pemilu, yakni nasional untuk Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan bersamaan dengan DPR dan DPD, serta lokal untuk memilih kepala daerah dan DPRD serta kabupaten atau kota yang dilakukan dua tahun setelah pemilu nasional. Adanya format tersebut, parpol-parpol dipaksa berkoalisi sebelum pemilu legislatif, sehingga terbentuk koalisi dengan ideology dan haluan politik yang satu dan menjadi besar.
Bab V, menjelaskan mengenai kegagalan negara dalam mengatur sistem demokrasi dan keberagaman yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Kegagalan yang dihadapi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh para penyelenggara negara, tetapi juga faktor masyarakat. Tidak adanya sosok yang patut diteladani, berkarakter dan nasionalis baik di tingkat negara maupun masyarakat. Padahal sosok tersebut penting dalam memberi contoh dan mewujudkan kehidupan kolektif bangsa kita yang nyaman, damai dan toleran.
Demokrasi yang didapatkan dari rezim otoriter Soeharto, seharusnya saling berhubungan dengan kebangsaan di dalam pluralitas keindonesiaan. Memberi keutuhan bagi bangsa bukan berakhir sia-sia akibat para penyelenggara kekuasaan gagal dalam mengelola keberagaman. Saling percaya, kerja sama dan dialog antara para pemegang kekuasaan mesti dijaga, dirawat dan dikelola sebagai pluralisme bangsa agar tidak menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Karena keberagaman yang dikelola dengan kolektif, melahirkan masyarakat dan bangsa yang adil, sejahtera dan damai.
Bab VI, membahas mengenai para calon pemegang kekuasaan masa pemilu 2014 tidak menampilkan sebuah terobosan yang mampu membawa perubahan baik bagi bangsa dengan membenahi segala persoalan krusial dan strategis. Melainkan, sibuk memburu dan mengutak-atik potensi popularitas dan elektabilitas. Ditambah lagi, masyarakat khususnya dari kelas menengah yang memilih diam di “zona nyaman” dari pada menjadi faktor perubahan politik. kelas menengah yang terdidik seperti akademisi, mahasiswa dan para aktivis gerakan tidak hanya sedikit dari jumlah tapi juga cenderung terpolarisasi.
Hal tersebut menunjukkan perlu dibangunnya suasana saling percaya, kerja sama dan konsolidasi di antara berbagai elemen masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi agar tidak sekedar menjadi wadah transaksional para elite politik. Mendesakkan perubahan kepada para penyelenggara kekuasaan yang lebih bertanggung jawab dalam hal itu. Untuk menuju bangsa Indonesia yang lebih adil dan nyaman bagi seluruh rakyatnya, maka dapat diwujudkan dengan warga negara yang merupakan pemilik kedaulatan politik yang selalu meneriaki dan menentang ketidak adilan, ketidakpedulian para elite terhadap masa depan bangsa.
Bab VII, membahas mengenai islam dan keindonesiaan pada masa pasca Soeharto. Demokrasi pasca Orde Baru memberi kesempatan bagi elemen masyarakat yang terbelunggu pada masa rezim otoriter Soeharto untuk mengaktualisasikan identitas mereka. Sebgai contoh, mengentalnya identitas keacehan di Tanah Rencong Aceh, melalui pemberontakan senjata yang dilakukan GAM,akhirnya terciptanya kedamaian dan pemberontakan untuk menguatkan identitas daerah lainnya. Selai itu, terjadi pula pada elemen politik Islam yang tidak hanya membentuk partai Islam berideologi Islam, tetapi juga membentuk kelompok, gerakan yang tidak berpartisipasi dalam proses politik formal dan tidak percaya sistem demokrasi sebagai solusi. Bila ditelusuri lebih jauh, munculnya kelompok, gerakan dan ideologi tersebut adalah wujud perasaan tersisih dan terasing para anggota dan pendukung dari sistem demokrasi.
Hal ini menunjukkan bila para penyelenggara negara mampu mengelola pluralisme dan multikulturalisme dengan benar dan tegakkan keadilan, maka munculnya kelompok-kelompok tertentu merupakan sebuah tantangan kecil dari keindonesiaan yang tengah dalam “proses menjadi”. Dengan maksud, kelompok-kelompok atau gerakan tersebut merasa tersisih dan terasingkan karena tidak mampu menghadapi perubahan sebagai keniscayaan sejarah peradaban. Dengan demikian, meskipun Indonesia merupakan negara mayoritas Islam, namun tidak berorientasi formalism Islam dalam kehidupan politik. Pada hasil pemilu pasca Soeharto menunjukkan, sebagian besar umat Islam memberi dukungan pada parpol nasionalis-sekuler dari pada parpol berbasis Islam.
Bab VIII, pada bab ini membahas mengenai permasalahan partai-partai dan sistem kepartaian. Atas dasar itu, ada beberapa bahan pertimbangan gagasan pembaruan partai menuju suatu sitem kepartaian yang diharapkan dapat memberi kontribusi bagi cita-cita bangsa dan kesejahteraan rakyat. Partai politik merupakan pilar dan institusi demokrasi yang penting selain lembaga lainnya seperti parlemen, eksekutif, yudikatif, pemilihan umum dan pers yang bebas. Namun tidak semua parpol memberi kontribusi positif pada sebuah bangsa. Samuel P. Huntington, meyebutkan bahwa hanya partai yang kuat dan terinstitusionalisasi yang menjanjikan yang dapat membentuk demokrasi yang lebih baik. Negara yang masih baru demokrasi, cenderung partai-partainya menjadi beban ketimbang solusi bagi permasalahan rakyat.
Ada beberapa pesan utama yang di sampaikan penulis terlepas dari setuju atau tidak mengenai gagasan dan usulan reformasi kepartaian. Pertama, penataan kehidupan politik ke depan hendaknya lebih terarah, konsisten dan konsepsional, sehingga perubahan tidak bersifat tambal-sulam. Kedua, setiap melakukan perubahan politik, tentunya akan memiliki dampak dan resiko. Sehingga, sebelum melakukan perubahan tersebut, perlu membaca dan mempersiapkan dengan komprehensif agar resiko tersebut dapat diperhitungkan lebih dini. Dan terakhir, dalam perubahan atau penyempurnaan UU maka perlu adanya serupa pilihan atas sistem kepartaian, misalnya koheren dengan pilihan atas sistem pemilu. Perlu diketahui pula, bila koherensi tidak selalu bisa menjamin pilihan benar-benar sesuai kebutuhan obyektif bangsa kita.
Bab IX, membahas mengenai problem kebijakan desentralisasi asimetris sebagai pilihan politik dalam agenda desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada konteks negara kesatuan tidaklah semudah dalam konteks negara federal. Sejumlah daerah seperti Aceh dan Yogyakarta memiliki relasi yang khusus dengan pemerintahan pusat sejak awal pembentukan Republik, sehingga ada kekhususan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Realitas politik-historis seperti inilah yang membelatarbelakangi Bung Hatta mengenai hakikat desentralisasi dan otonomi daerah.
Desentralisasi yang sepenuhnya sama dan seragam tidak sesuai bagi Indonesia yang sangat beragam. Sebaliknya pula, desentralisasi sepenuhnya asimetris belum tentu menjadi solusi. Maka dari itu, penegakan desentralisasi asimetris dimungkinkan melalui penempatan obyektif atas potensi sumber daya dan daya dukung daerah. Pengimplementasi desentralisasi asimetris tidak hanya dan tidak harus berujung otonomi khusus atau otonomi sangat luas, melainkan juga otonomi luas dan terbatas.
Buku ini menjelaskan secara bertahap mengenai masalah-masalah yang muncul pasca Orde Baru. Tentunya berkaitan dengan pemegang kekuasaan pada masa reformasi, khususnya pada tiga orang prsiden, yaitu Wahid, Megawati dan Yudhoyono. Tidak hanya membahas mengenai sistem yang ditetapkan namun juga munculnya gerakan atau kelompok-kelompok yang menjadi tantangan. Serta kebijakan yang dibuat yang memiliki dampak bagi bangsa ke depannya.
Kaitan dengan masa saat ini:
Buku ini menggambarkan berbagai tantangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru, seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan kegagalan konsolidasi kekuatan politik. Meskipun buku ini ditulis pada 2014, relevansinya masih terasa dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. Beberapa masalah utama yang diangkat dalam buku, seperti korupsi dan tata kelola pemerintahan, masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia hingga kini. Sistem demokrasi Indonesia yang berbasis multipartai dan sering kali menghadirkan koalisi yang tidak solid, seperti yang dialami di era Presiden Yudhoyono, juga tetap terjadi pada era pemerintahan Jokowi. Elite politik masih sering terjebak dalam dinamika politik transaksional, yang berdampak pada efektivitas pemerintahan.
Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan politik identitas dan bagaimana demokrasi membuka ruang bagi munculnya identitas etnik, agama, dan daerah yang dapat mengancam persatuan bangsa. Fenomena ini masih relevan, terutama dengan meningkatnya politik identitas di berbagai wilayah Indonesia, yang kadang-kadang memperdalam polarisasi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Syamsuddin Haris juga menekankan pentingnya warga negara yang aktif dan sadar akan hak serta tanggung jawab politik mereka. Dalam konteks saat ini, peran masyarakat sipil tetap vital dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam hal kebebasan berpendapat dan pemilu yang lebih terbuka, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan demokrasi yang substansial, di mana hak-hak politik dan ekonomi masyarakat terlindungi dan korupsi diberantas secara efektif.
Dengan demikian, buku ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika demokrasi Indonesia di masa sekarang, khususnya dalam melihat bagaimana masalah-masalah yang dihadapi sejak era reformasi terus berlanjut dan memengaruhi arah perkembangan politik di Indonesia.
Penulis adalah Naily Jannati mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Syiah Kuala (USK).
Editor: Putri Izziah