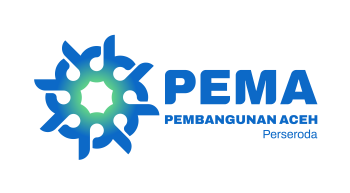Opini | DETaK
Sekolah sejatinya tidak hanya sekedar ruang untuk belajar akademik, tetapi juga tempat pembentukan karakter dan moral. Dalam proses ini, kepala sekolah memiliki peran yang begitu besar, seperti memastikan tata tertib ditegakkan dan seluruh siswa diperlakukan dengan adil. Peran tersebut bukan sekedar jabatan struktural, melainkan merupakan amanah untuk menjaga martabat pendidikan. Tanpa ketegasan seorang kepala sekolah, aturan hanyalah sebuah tulisan di atas kertas.
Namun, peran itu kini diuji. Kasus pencopotan seorang kepala sekolah di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 16 September lalu menjadi sorotan publik. Ia diduga dicopot karena menegur seorang murid yang mengendarai mobil ke sekolah. Bukan sembarang murid, melainkan anak dari seorang pejabat. Teguran itu seharusnya dianggap wajar dan mendidik, namun akhirnya berujung pada mutasi jabatan.
Kita sebagai mahasiswa, para calon guru dan pendidik, belajar bahwa integritas merupakan fondasi yang paling utama. Namun kenyataan pahit seperti ini mengundang beberapa pertanyaan dalam diri:
1. Apakah hukum dan aturan hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan?
2. Apakah dunia pendidikan benar-benar memberikan ruang bagi orang yang berani jujur demi menegakkan aturan?
3. Apakah aturan sekolah bisa dibeli oleh status sosial?
Peristiwa ini seolah menegaskan bahwa prinsip disiplin dan aturan seketika runtuh dihadapan kekuasaan.
Di lihat dari sudut pandang kepala sekolah, tindakan menegur siswa jelas merupakan bagian dari tugas seorang kepala sekolah maupun para guru dibawahnya. Menegur bukan berarti menjatuhkan harga diri seorang murid, melainkan cara untuk menanamkan kedisiplinan. Kini Kepala sekolah berada pada posisi yang sulit, jika ia membiarkan pelanggaran yang di lakukan begitu saja, maka integritas sekolah akan runtuh. Namun, jika ia menegur, profesinya bisa terancam karena berhadapan dengan kekuasaan. Situasi ini menjadi dilema moral dan professional. Bagaimana mungkin seorang pendidik bisa bekerja semaksimal mungkin jika setiap langkahnya diawasi oleh bayang-bayang kekuasaan?
Jika dilihat dari sudut pandang murid sendiri, kasus ini memberikan pelajaran yang salah. Anak-anak butuh contoh bahwa aturan berlaku pada setiap orang tanpa memandang status sama sekali. Jika mereka melihat ada siswa yang dilindungi meskipun melanggar aturan tersebut, sedangkan pendidik yang menegakkan aturan justru dihukum, maka kepercayaan mereka terhadap sekolah akan luntur. Hal ini dapat berdampak sangat bahaya, murid bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa kedisiplinan bisa dinegosiasikan, atau posisi sosial lebih berharga daripada sebuah kejujuran.

Lalu, bagaimana seharusnya cara seorang guru atau kepala sekolah menegur murid di era sekarang?
Pertanyaan ini penting. Di masa lalu, cara menegur seorang guru terhadap murid sering dilakukan dengan keras, bahkan tak jarang menggunakan hukuman fisik. Namun, pendekatan semacam itu sudah tidak relevan lagi di era saat ini. Pendidikan modern menekankan pada pendekatan persuasif, seperti memberi pemahaman, berdialog, dan membangun kesadaran murid tentang konsekuensi dari tindakannya. Teguran seharusnya tetap tegas, tetapi tidak sampai melukai secara fisik. Artinya, disiplin tetap bisa ditegakkan tanpa adanya kekerasan.
Dalam kasus Prabumulih, teguran kepala sekolah pada dasarnya adalah bagian dari pendidikan karakter. Tidak ada unsur kekerasan yang dilaporkan, hanya teguran wajar untuk memahami siswa agar tau batasannya. Sayangnya, teguran tersebut terhantam pada penghalang besar yaitu privilege.
Apakah privilege anak pejabat berlaku dalam menerapkan sebuah aturan?
Privilege anak pejabat sering kali menjadi topik yang sensitif. Privilege pada dasarnya keuntungan atau akses khusus yang dimiliki oleh seseorang karena status keluarganya, bukan karena usahanya sendiri. Dalam konteks pendidikan, privilege anak pejabat dapat muncul dalam perlakuan istimewa, seperti bebas dari konsekuensi, lebih dilindungi, bahkan kebal terhadap aturan yang berlaku. Masalahnya, privilege seperti ini justru merusak prinsip dasar pendidikan, yaitu keadilan.
Ketika anak pejabat bisa melanggar aturan sesuka hati, namun siswa lain dituntut untuk patuh terhadap aturan, maka sekolah seketika menjadi ruang yang timpang. Bukan lagi tempat belajar bersama secara seimbang, tetapi menjadi panggung ketidakadilan yang memperkuat jurang sosial. Privilege ini, jika dibiarkan, akan menggerus nilai-nilai integritas dan kesetaraan yang seharusnya ditanamkan sejak dini.
Sebagai mahasiswa yang memperhatikan isu, ini adalah alarm keras. Pemerintah daerah dan otoritas pendidikan seharusnya melindungi pendidik yang berkredibilitas bukan malah menghukumnya. Kepala sekolah seharusnya mendapat apresiasi karena berani menegur siswa yang memiliki privilege sebagai anak pejabat dan menunjukkan contoh keadilan yang baik terhadap murid lainnya, bukan justru dipindahkan karena keberaniannya dianggap menganggu kepentingan sepihak.
Teguran merupakan hak sekaligus kewajiban seorang guru maupun kepala sekolah. Selama dilakukan tanpa kekerasaan, teguran adalah bagian penting dari pendidikan berkarakter. Jika teguran seperti ini berbuah hukuman, maka yang tersisa hanyalah, aturan hanya berlaku bagi yang lemah, dan kekuasaan melindungi yang kuat.
Kasus ini semestinya menjadi momentum refleksi, apakah kita ingin sekolah menjadi benteng moral yang adil terhadap semua siswa, atau hanya menjadi tempat yang tunduk pada privilege? Jawabannya hanya ada di tangan kita bersama.
Penulis adalah Naisya Alina, Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah kuala
Editor : Rimaya Romaito Br Siagian