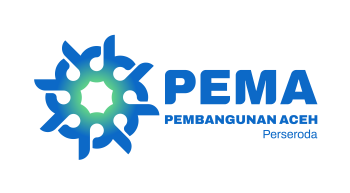Opini | DETaK
Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan tren berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan sekali klik, penggemar bisa mengedit foto polaroid seolah-olah mereka berpose bersama idola. Tren ini dengan cepat meluas dan dianggap sebagai cara baru menyalurkan ekspresi diri, bahkan mewujudkan fantasi yang selama ini hanya bisa dibayangkan.
Namun, di balik wajah kreatif itu, ada masalah serius. Apa yang awalnya dianggap hiburan kini semakin sering disalahgunakan. Wajah idola dimasukkan ke dalam foto dengan pose sensual atau konteks yang tidak pantas. Dampaknya jelas: bukan sekadar lucu-lucuan, melainkan merendahkan martabat orang yang fotonya dijadikan objek manipulasi.

Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Buktinya, banyak publik figur yang mulai angkat suara. Pada September 2025, beberapa pemain Timnas Indonesia, seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Sandy Walsh, secara terbuka meminta penggemar untuk berhenti membuat foto editan AI. Foto-foto itu, yang tersebar di media sosial, menampilkan mereka dalam pose mesra dan intim yang melewati batas kesopanan. Sandy Walsh bahkan menyampaikan kekhawatiran bahwa manipulasi semacam ini bisa menimbulkan kesalahpahaman di masa depan.
Tak hanya itu, musisi Baskara Putra akrab disapa Hindia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan wajahnya digunakan dalam konten AI, apa pun niat penggemarnya. Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata bahwa tren polaroid AI telah menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan kegelisahan psikologis, bagi publik figur.
Sayangnya, dalih “sekadar hiburan” kerap dipakai untuk menormalisasi praktik ini. Penggemar lupa bahwa publik figur juga manusia yang punya hak privasi. Benar, mereka memang hidup di ruang publik. Tetapi publikasi tidak sama dengan kepemilikan wajah. Bahkan secara hukum, Indonesia melalui UU ITE Pasal 27 dan KUHP Pasal 45 mengatur sanksi bagi penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau merugikan orang lain. Artinya, penggunaan wajah idola dalam konteks tak senonoh berpotensi masuk ke ranah pidana.
Kita yang menyebut diri sebagai penggemar seharusnya tidak hanya memikirkan kesenangan sesaat, tetapi juga memikirkan bagaimana keadaan idola kita di masa depan. Di era di mana informasi menyebar begitu cepat dan mudah dipelintir, ruang untuk lahirnya hoaks semakin terbuka lebar. Bayangkan jika foto-foto editan yang melampaui batas itu kembali muncul di kemudian hari, dibungkus dengan narasi yang merusak reputasi dan karier sang idola. Apa yang hari ini kita anggap sekadar “hiburan” bisa berubah menjadi bom waktu yang siap meledakkan citra mereka kapan saja.
Di titik ini, kita perlu menyadari bahwa dilema etika teknologi bukanlah masalah baru. Sejarah selalu mencatat bahwa setiap kali hadir inovasi besar, selalu ada konsekuensi sosial yang menyertainya. Televisi pernah dituding merusak moral generasi muda, internet dianggap ladang hoaks, dan kini giliran AI yang disorot. Bedanya, kecerdasan buatan memiliki daya reproduksi dan penyebaran jauh lebih cepat. Hanya dalam hitungan detik, konten bisa viral dan sulit dikendalikan, sehingga dampaknya lebih luas dan mendalam.
Lantas, siapa yang patut disalahkan? Hanya penggemar, atau juga platform yang membiarkan? Jika ditelisik lebih jauh, media sosial jelas punya peran besar dalam membesarkan tren ini. Perusahaan AI pun tak lepas dari keterlibatan karena menyediakan teknologi yang digunakan. Namun, tetap saja, kendali utama ada di tangan kita sebagai pengguna. Kita yang menentukan bagaimana teknologi dipakai apakah sebagai sarana kreatif yang sehat, atau justru menjelma alat eksploitasi.
Ironisnya, sebagian orang justru merasa bangga jika editan mereka viral, tanpa memikirkan konsekuensi bagi pihak yang wajahnya dijadikan objek. Fenomena ini memperlihatkan betapa rendahnya kesadaran etis digital di masyarakat kita. Padahal, literasi digital seharusnya bukan sekadar kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga memahami dampak moral dan sosial dari penggunaannya.
Sayangnya, banyak penggemar yang gagal bersikap bijak. Tren yang seharusnya bisa menjadi ruang positif sekadar berpose seolah di samping idola bergeser menjadi praktik yang melecehkan. Perusahaan AI mungkin hanya berupaya memberi inovasi teknologi terbaik, tetapi tanggung jawab moral tetap berada pada pengguna. Kita yang mengarahkan teknologi ini: ke arah yang bermanfaat, atau ke jurang penyalahgunaan.
Pada akhirnya, tren polaroid AI menempatkan kita pada persimpangan antara kreativitas dan etika. Teknologi memang membuka ruang baru bagi ekspresi, tetapi tanpa batas, ia bisa merusak martabat manusia. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah ini hiburan atau bukan, melainkan apakah kita rela menjadikan wajah orang lain sebagai bahan eksploitasi demi kesenangan pribadi?
Jika kita terus menormalisasi perilaku ini, maka yang rusak bukan hanya reputasi para publik figur, melainkan juga moral publik itu sendiri. Sebab, sekali kita membiarkan imajinasi berjalan tanpa etika, kita sedang membuka pintu bagi pelecehan digital yang lebih masif di masa depan.
Karena itu, tanggung jawab ada di tangan kita semua pengguna, platform, dan penyedia teknologi. Kreativitas seharusnya membebaskan, bukan melukai. Etika digital tidak boleh hanya menjadi jargon, melainkan praktik nyata yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan begitu, teknologi dapat benar-benar menjadi ruang aman untuk berkreasi, tanpa harus mengorbankan martabat manusia.
Penulis bernama Kamilina Junita Damanik, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosil dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Khalisha Munabirah