Aceh. Musim-musim telah berkhianat pada kita dan had datang yang sebenarnya. Seperti kita yang berkhianat pada diri kita sendiri. Sekarang adalah kita sedang terlempar kembali pada satu titik paling rawan, titik tanda bahwa akan pecah sebuah talian. Aceh, hidup di atasmu umpama meniti hari dalam kemarau yang panjang tanpa lanang sepercik hujan. Langit sangar, kita sangar, hari adalah gumulan hingar bingar. Di sini, yang ada hanya kebun damai enggan dijaga. Seonggok harapan adalah kesia-siaan belaka. Aceh, tuan gagah dengan darah fisabilillah yang entah bagaimana mahfum dan tafsirnya. Bilamana hadir sebuah keributan, maka golongan satu dan golongan lainnya mesti berebut cepat mengusung nama Tuhan dan agama. Kita adalah seumpama tanah yang tercipta dari lazuardi yang dipanggang di bawah matahari pada rentang jangka yang lama; keras, indah, namun mengucur. Memerahkan sungai semerah saga, memerahkan laut semerah saga, memerahkan gunung semerah saga, memerahkan kampung semerah saga. Aceh, seonggok kehidupan tanpa udara hutan legam, yang ada hanya kemarau dan malam.
Di depan rumah, pada bangku panjang, Ayah dan Cut Wan berseteru tentang pilihan mereka nun beberapa purnama lagi. Terdengar beberapa kali benturan pemikiran keduanya. Ayah mempertahankan pilihannya, pun Cut Wan begitu juga. Maka, di bawah geliat kemarau ya ng menggulung kampung tanpa ampun, keduanya masih saja tak rukun. Ini masalah pilihan. Masalah ideologi. Namun, bila masing memaksa pilihannya pada yang berbeda pandangan, hilang sudah demokrasi. Ah, politik kampung kami ini. Begitulah, ayah dan Cut Wan tak menemui titik temu pikiran. Bagaimana mungkin bertemu, mereka memilih dua orang yang berbeda dari golongan yang sedang berseteru.

Cericit pintu terdengar. Kulihat Ayah bermuka masam. “Si Wan itu sulit sekali diberikan wejangan. Suka membantah. Kau jangan sampai terpengaruh dengan cara pikirnya, bisa celaka.” kata Ayah sembari berlalu begitu saja. Aku hanya diam, kukira untuk apa terlalu kuturutkan keinginan salah satu dari mereka. Aku mesti berpikir bagaimana mengisi sawah dengan air. Sayang sekali padi kami. Jika hujan tak lanang seminggu lagi dan air di sungai yang melintas kampung kami kering, maka tentu semua padi akan mati. Ah, kemarau terlalu tega hati.
Petang, ketika ayah dan Wak Leman sedang terlibat percakapan seru tentang pilihan mereka yang kebetulan sama, aku turun dari rumah menuju sawah. Padi-padi orang kampung seperti seekor serigala yang meraung. Condong menatap langit dan menguning pada masa baru dua pekan tanam. Ini musim terkutuk. Namun, kukira para orang kampung tak mau ambil suntuk. Untuk saat seperti ini, mereka lebih mau memfokuskan diri pada acara jelang pilih memilih. Ikut rapat calon dewan di sana sini bagi mereka lebih berguna dari pada memikirkan persolan musim, persoalan padi. Kepulan asap di tungku kayu mereka tetap akan terlihat hingga panen usai, pun padi mereka mati bilamana calon usungan mereka menang nanti. Maka mereka enggan memerhatikan musim ini. Lalu, siapakah yang berkhianat sebenarnya, orang kampung kami atau musim yang sombong ini.
Ayah juga begitu. Urusan padi semua terpulang pada kami. Ia perlu memikirkan dapur dan ini masanya meraup untung dari calon dewan sebesar-sebesarnya. Sedang tentang kemarau dan padi, sama sekali ia tak peduli. Petang ini, di pematang sawah kami kulihat beberapa padi yang mulai mati. Air semakin sulit didapati. Namun, dalam pikiranku yang sedang diamuk keibaan, muncul pula pertanyaan, apa maksud Ayah pada bahaya jika menuruti cara pikir Cut Wan.
Malam datang dengan cepat dan sigap. Aku belum menemukan jawaban. Dan dalam kelelahan mengalirkan air dalam petak sawah kami tadi petang, aku terlelap. Malam yang sunyi. Kami dikejutkan suara ribut di pekarangan. Dalam keributan dan kebosanan aku bangun. Ibu duduk di muka pintu depan rumah kami dengan wajah tegang, Ayah gemetaran. Seorang lelaki tergantung dengan lidah terjulur di dahan pohon kuini depan rumah kami adalah Wak Leman. Aku ternganga. Cut Wan dan segenap warga berdiri tak jauh dari sana dengan wajah seakan tak percaya. Sayup kata terdengar ini erat kaitannya dengan pilihan calon dewan. Ah, Aceh, kemarau yang memaksa padi kami haus ini belum lanang, adakah keributan ini kembali telah dimulai?
*Penulis adalah mahasiswa Gemasastrin Unsyiah.

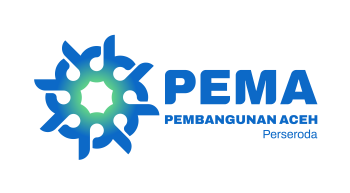


![[LENSA] Fasilitas USK yang Direnovasi Pasca PON](https://detakusk.com/wp-content/uploads/2024/09/detak-lensa1-238x178.jpg)







