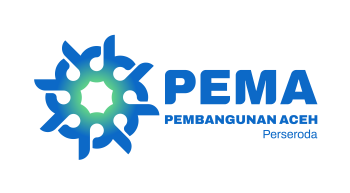Opini | DETaK
Pemberedelan 12 media massa pada tahun 1974 seusai peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) menjadi awal mula dari bisunya dunia pers Indonesia di era orde baru. Peristiwa itu bermula ketika Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, berkunjung ke Indonesia. Masyarakat menilai bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk kebijakan ekonomi pemerintah Soeharto yang terlalu condong kepada investasi asing. Tak tinggal diam, mahasiswa sebagai ujung tombak masyarakat pun memutuskan beraksi dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di jalanan kota Jakarta.
Kerusuhan pun tak terelakkan. Aksi pembakaran dan perusakan segala kendaraan maupun gedung dilancarkan oleh sebagian oknum demonstran, terutama yang berhubungan dengan produk jepang. Akibatnya, beberapa aktivis ditangkap, dan bahkan juga terjadi penembakan senjata api oleh aparat yang dilepaskan ke arah mahasiswa demi mengamankan kericuhan yang terjadi. Begitu pula dengan media massa yang ikut berkomentar serta mengkritik pemerintah atas kejadian tersebut, mereka pun dicabut surat izin terbit dan surat izin cetaknya. Ini lah yang menjadi penyebab awal tunduknya dunia pers Indonesia terhadap pemerintah era orde baru.

***
Sebenarnya, pengontrolan politik terhadap pers memang telah dimulai semenjak awal pemerintahan Soeharto berdiri. Bukan hanya dunia pers, seluruh elemen pemerintahan juga dibuat lebih tegas dengan adanya peraturan-peraturan baru. Peraturan-peraturan baru terus bermunculan, seperti UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 4 Tahun 1967 teruntuk pers. Pers juga diharuskan memiliki STT (Surat Tanda Terdaftar) dan SIT (Surat Izin Terbit) sebagai tanda legalnya mereka dalam kancah penyiaraan informasi.
Meskipun di sekitaran tahun tersebut belum bermunculan isu mengenai pengekangan pers, tapi benih-benih yang tak disadari telah tampak melalui regulasi-regulasi yang dibentuk. Masyarakat sebelumnya mengira bahwa itu merupakan strategi pemerintah guna mencapai kebebasan pers yang dijanjikan, setelah sebelumnya rusak akibat demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Namun, semenjak peristiwa malari terjadi, semua anggapan itu berubah total. Suasana dunia pers di Indonesia menjadi lebih mencekam dengan dikeluarkannya aturan baru UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers. Di samping itu, pemerintah juga membuat kebijakan baru dengan menganti SIT dengan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang hanya dapat dikeluarkan oleh Departemen Penerangan.
Apa yang pembaca budiman pikirkan terkait hal ini? Ya, tepat sekali. Dunia pers yang seharusnya mencerminkan kebebasan berpendapat seakan terpenjara di dalam jeruji permainan politik para penguasa. Tak sampai di situ, kasus pembredelan serupa juga kembali terjadi pada tahun 1994. Tiga majalah besar ternama di Indonesia dicabut SIUPP-nya oleh Departemen Penerangan, yakni majalah Tempo, Detik, dan Editor. Pemerintah yang saat itu membeli kapal perang bekas sebanyak 39 unit dari Jerman Timur dengan harga USD 1,1 miliar menjadi sorotan publik. Bukan tentang kapal perangnya, melainkan tentang jumlah harganya yang melambung tinggi sebanyak 62 kali lipat dari harga sebenarnya, yaitu USD 12,7 juta. Ketiga majalah tersebut pun buka suara dengan mengkritik persoalan ini sehingga berujung pada pelarangan penyiaran.
Menurut sudut pandang pemerintah, pelarangan tersebut merupakan tindakan urgen dalam menertibkan pergerakan pers yang dinilai terlalu “liar”. Soeharto menganggap bahwa ada urusan yang tidak elok dibahas oleh pers karena ia menganggap pers tidak paham mengenai hal tersebut, seperti kasus pembelian kapal perang bekas Jerman Timur. Dikhawatirkan pers akan menimbulkan permusuhan antara kalangan rakyat dengan pejabat pemerintahan melalui pemberitaan yang diklaim bersifat subjektif.
Alasan lainnya dibalik ketatnya pengawasan terhadap gerak-gerik pers adalah untuk merealisasikan target pemerintah yang telah disusun. Menurut pemerintah, mengedepankan pembangunan ekonomi merupakan langkah paling efektif dalam memajukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukanlah stabilitas politik untuk menyokong pembangunan ekonomi yang dimaksud. Supaya stabilitas politik dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah harus menjadi pengendali tunggal dalam memainkan kekuatan politik. Pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya perpecahan politik dengan menggunakan pers sebagai media utamanya. Pers dipersilahkan menyiarkan berita-berita baik sebagai penunjang program pemerintah dan dilarang menyiarkan berita-berita buruk seputar lika-liku pemerintah.
Apapun alasan pemerintah orde baru nyatakan terkait upaya pengekangan pers, tetap saja itu tidak bisa dibenarkan. Malah dengan begitu, citra Indonesia sebagai negara demokrasi akan ternodai dengan embel-embel “pers pancasila” sebagaimana yang digaungkan oleh para petinggi orde baru. Hak kebebasan berpendapat yang merupakan salah salah satu aspek yang dilindungi oleh UUD 1945 serasa dikebiri dengan gampangnya. Pers tidak lain hanya dituntut untuk menjadi alat pemerintah dalam mengharumkan reputasinya dibalik busuknya permainan yang mereka sembunyikan. Pembungkaman pers selama orde baru merupakan bentuk dari cacatnya perpolitikan negara yang terjadi.
***
Menurut hemat penulis, menciptakan kebebasan pers merupakan suatu langkah bijak dan benar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang beragam. Pers yang terbuka akan menjadi pengingat sekaligus penasehat bagi pemerintah dalam menjalani roda pemerintahannya. Jika suatu media massa melakukan penyimpangan dalam penyiaran informasi, maka seharusnya kasus tersebut diarahkan ke ranah hukum, bukan malah langsung dicabut eksistensinya. Melalui sejarah masa silam, kita bisa belajar bahwasanya pengekangan pers di masa orde baru dapat menciptakan rasa tidak percaya kepada pemerintah.
Perayaan hari pers nasional pada 9 Februari 2021, kita harus paham bahwa menjaga kebebasan pers di era reformasi ini masih diperlukan. Bukan tidak mungkin bila suatu hari nanti kebebasan pers akan direnggut kembali oleh oknum-oknum yang mengaku “demokratis”. Selama kita bersatu dalam memperjuangkan dan mempertahankan asas-asas demokrasi bercirikan Pancasila, maka ancaman seperti itu akan mudah teratasi. Mari kita rapatkan barisan bersama, selalu lihai dalam membaca situasi yang ada, dan cepat tanggap dalam menormalisasikan masalah yang mencuat agar negara yang yang kita cintai ini senantiasa terhindar dari segala ancaman yang mengintai.[]
Penulis bernama Muhammad Abdul Hidayat. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Syiah Kuala, angkatan 2019. Ia merupakan salah satu anggota magang di UKM Pers DETaK.
Editor: Cut Siti Raihan