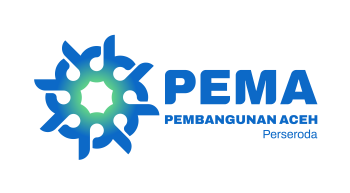Opini|DETaK
Berdirinya persada Tanah Iskandar Muda yang kini dalam situasi aman dan damai tak terlepas dari buah hasil perjalanan konflik yang berkepanjangan. Konflik yang paling dahsyat mulanya terjadi sejak kedatangan Belanda ke Aceh dengan membawa praktik kolonialisme dan imperialisme. Kedatangan Belanda yang memiliki maksud untuk menduduki tanah Aceh ini telah menyebabkan meletusnya perang Aceh melawan Belanda yang resmi diproklamirkan pada 26 Maret 1873. Peperangan yang berkepanjangan ini akhirnya berhasil mengalahkan Belanda. Namun, silih waktu berganti, setelah kolonialisme Belanda kalah, Jepang pun datang dan mulai melancarkan aksi kolonialisme di Indonesia. Perang melawan kolonialisme Jepang dimulai pada tahun 1942 yang pada akhirnya perlawanan ini dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Kekalahan Jepang untuk menduduki Tanah Air Indonesia ini merupakan awal dari cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Setelah berhasil mengalahkan kolonialisme Jepang, pada tahun 1945 Indonesia resmi merdeka ditandai dengan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang digemakan oleh Soekarno dan M. Hatta sebagai representatif bangsa.
Waktu demi waktu silih berganti, Indonesia yang masih berumur sebiji jagung kembali dihadapkan konflik. Namun, konflik kali ini terjadi dengan bangsa sendiri, termasuk di dalamnya konflik dengan masyarakat Aceh. Kurang lebih delapan tahun pascakemerdekaan, pada 20 September 1953 konflik DI/TII meledak di Aceh. Tgk. Daud Beureueh memimpin gerakan DI/TII di Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang dipelopori oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai bentuk respon dari berbagai kekecewaan terhadap pusat atas ketimpangan sosial dan keadilan yang ada di Aceh waktu itu. Kendati demikian, hari demi hari yang dilewati dengan berbagai letusan senjata yang bergema di Aceh akhirnya berujung pada perdamaian yang disepakati di Ikrar Lamteh pada 7 Maret 1957. Dari perjanjian tersebut terciptalah perdamaian antara DI/TII Aceh dengan Indonesia yang ditandai dengan kembalinya Aceh sebagai provinsi otonom yang sebelumnya dileburkan pada Provinsi Sumatera Utara.

Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menimbulkan dampak yang berarti diberbagai sendi kehidupan masyarakat terutama pada kondisi pendidikan yang mengalami stagnasi. Melihat hal itu, kondisi pendidikan yang sudah lama stagnan, pemerintah berinisiatif untuk membentuk Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) pada tanggal 21 April 1958 yang bertujuan untuk mengadakan pembangunan dalam bidang rohani dan jasmani guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Aceh. Salah satu program yang dicanangkan oleh YDKA adalah mendirikan kampung pelajar/mahasiswa di Ibu Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kala itu. Pembangunan Kampus Kopelma Darussalam tersebut dimulai dari 17 Agustus 1958 dan diresmikan pada 2 September 1959. Pembangunan Kampus Kopelma Darussalam tersebut telah melahirkan tiga perguruan tinggi, yaitu Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (IAIN Ar-Raniry), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk Chik Pante Kulu (STAI Tgk. Chik Pante Kulu).
Pembangunan ketiga kampus tersebut memiliki landasan filosofis tersendiri, Unsyiah sebagai kampus ilmu pengetahuan umum, IAIN Ar-Raniry sebagai kampus ilmu pengetahuan agama Islam, dan STAI Tgk. Chik Pante Kulu sebagai pendidikan tinggi dari dayah (pesantren) yang ada di Aceh. Pembangunan tiga kampus tersebut merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Dari titik pembangunan Kopelma Darussalam inilah menjadi sebuah upaya dalam menyongsong kembali peradaban Aceh yang sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), Aceh dikenal dunia sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara.
Kopelma Darussalam sebagai Antitesis dari Darul Harbi
Darussalam sendiri didefinisikan sebagai sebuah negeri atau tempat yang damai dan tentram, tentunya Darussalam ini juga dicitrakan sebagai sebuah tempat yang sejuk. Kata Darussalam ‘tempat yang sejuk’ ini diciptakan sebagai antitesis dari kata Darul Harbi yang berarti ‘tempat tidak damai’ yang merupakan suatu deskripsi terhadap keadaan Aceh silam yang selalu bergelut dengan konflik dan peperangan. Bedirinya Kopelma Darussalam sebagai rekonstruksi peradaban Aceh yang telah lama terkikis oleh berbagai peristiwa zaman merupakan ide dari tokoh-tokoh intelektual Aceh pada masa itu. Mereka menggagas ide serta visioner dalam mendorong peradaban Aceh dengan membangun tiga perguruan tinggi.
Pembangunan ketiga perguruan tinggi tersebut ditargetkan di atas tanah yang kosong atau terbengkalai karena faktor ditinggalkan oleh pemiliknya atau yang dikenal dengan istilah erpacht. Awalnya pembangunan dicanangkan berada di tanah erpacht daerah Keutapang Dua, namun karena luas wilayahnya yang tidak ideal maka dicarilah lahan erpacht lain yang berada di rumpit. Lahan ini merupakan bekas tanah (erpacht) N.V Rumpit milik keluarga T. Nyak Arif (Ramadan KH, 1995). Karena lahannya sangat luas dan ideal untuk mendirikan tiga kampus, lokasi ini akhirnya dipilih untuk dijadikan sebagai lahan berdirinya Kopelma Darussalam.
Pembangunan Kopelma Darussalam yang juga dikenal sebagai jantong hatee rakyat Aceh ini juga merupakan bentuk pengorbanan rakyat Aceh yang turut serta bahu membahu membangun Kota Pelajar Mahasiswa. Bedirinya Kopelma Darussalam sebagai daerah yang cinta akan kedamaian ini juga bertujuan untuk menghilangkan stigma Aceh yang dicap sebagai Darul Harbi, yaitu daerah yang selalu terjadi peperangan atau lahan pertikaian. Oleh karena itu, pembentukan Kopelma Darussalam sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual dan senantiasa mengedepankan moral. Selain itu, cita-cita Aceh sebagai pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara dapat diwujudkan kembali melalui pembangunan Kopelma Darussalam.
Romantika Pembangunan Kopelma Darussalam
Pembangunan Kopelma Darussalam memiliki berbagai romantika yang terus bergulir dari masa ke masa. Pada awal pembentukannya, ide ini sempat ditolak oleh pemerintah pusat pusat dengan dalih pembangunan infrastruktur publik dan ekonomi kerakyatan lebih penting dari pada membangun sebuah kampus. Padahal, dengan pembangunan kampuslah dapat merekonstruksi peradaban. Dinamika juga terjadi berawal dari peninjauan tanah erpacht Rumpit di daerah Lamnyong yang kurang lebih luasnya 181,3 hektare. Awalnya tanah erpacht ini diberikan hak kelolanya pada Johan George Goethals. Tanah tersebut tercatat dalam naskah hak tanah tanggal 22 Juli 1905 atas namanya, dan kemudian hak tanah erpacht di setor kepada NV. Landbouwonderneming dengan naskah hak tanah tanggal 17 Februari 1921 No. 15, dan akan habis temponya pada 21 Juni 1980. Kendati demikian, sebelum habis hak pengelolaan, tanah tersebut sudah terbengkalai tidak digarap oleh pemiliknya lagi dan tidak dibayar pajaknya, maka diajukan pembatalan sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1956). Oleh karena itu, diambil alihlah pembangunan Kopelma Darussalam dan dilakukan ganti rugi kepada penduduk setempat yang telah lama menggarap tanah tersebut.
Setelah selesai pembangunan Unsyiah dan IAIN Ar-Raniry sekitar tahun 1972, muncullah masalah lainnya. Ahli waris Teuku Nyak Arief mengaku sebagai pemilik tanah seluas 181,3 hektar tersebut sehingga akhirnya mereka mengajukan bukti valid dan konkret terkait kepemilikan tanah dan menuntut ganti rugi sebesar Rp40.000.000. Apabila ganti rugi tersebut tidak dapat dipenuhi maka ketiga kampus yang berada di lingkungan Kopelma Darussalam terancam hilang eksistensinya dari peradaban Aceh. Awalnya, ganti rugi ditagih kepada IAIN Ar-Raniry yang bernaung di bawah Depertemen Agama, namun Depag tidak mempunyai anggaran untuk membayar itu. Kemudian disodorkan kepada Unsyiah yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari pendanaan. Dana sebesar Rp32.625.000 akhirnya berhasil didapatkan dan pada 3 September 1975 diserahkan kepada T. Syamsulbahri, SH., selaku ahli waris Teuku Nyak Arief.
Setelah permasalahan ganti rugi tanah selesai, muncul lagi persoalan lain, yaitu terkait hak kepemilikan tanah seluas 181,3 hektare karena seluruh biaya ganti rugi dilakukan oleh Unsyiah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan IAIN Ar-Raniry berada di bawah Departemen Agama. Namun, persoalan itu berhasil dituntaskan oleh Prof. Ibrahim Hasan pada tahun 1980-an dengan membagi proporsi wilayah dengan batas tertentu, yaitu Unsyiah seluas 132,43 hektarnya di rumah, IAIN Ar-Raniry seluas 35,75 hektar, proyek pengaturan dan pemeliharaan Krueng Aceh 7,46 hektar, dan pelebaran jalan 5,66 hektaran (Berdasarkan Data Badan Pertanahan Nasional Kanwil Aceh,1992). Maka dengan kebijakan yang dilakukan oleh Prof. Ibrahim Hasan membuat Kopelma Darussalam menjadi hangat kembali. Meskipun luas tanah sudah dibagi sesuai dengan batas yang jelas, tetapi dalam realitanya masih ada fasilitas IAIN Ar-Raniry waktu itu berada di wilayah Unsyiah. Namun, hal itu tidak menjadi persoalan karena esensi pembangunan Kopelma Darussalam berasaskan persaudaraan dan gotong royong.
Perseturan kepemilikan tanah ini kembali muncul sejak satu tahun belakangan ini, suasana Kopelma Darussalam menjadi dingin karena fasilitas kampus UIN Ar-Raniry yang berada di wilayah Unsyiah menjadi polemik sampai saat ini, juga mempertimbangkan status perguruan tinggi yang sama-sama sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang menuntut penjelasan terhadap aset masing-masing kampus. Jika kita bercermin pada khittah pembangunan Kopelma Darussalam dan penyelesaian persoalan dengan sangat arif dan bijaksana yang dilakukan para pendahulu, maka sudah seyogyanya hubungan persaudaraan ini terus dibina dan dijaga, karena founding father dan Rakyat Aceh membangun Kopelma Darussalam dengan semangat gotong royong demi merekonstruksi peradaban yang telah tereduksi. Maka persoalan ini sudah saatnya diakhiri dengan konsep “musyawarah” dan “islah” demi mewujudkan Darussalam sejahtera di persada Tanah Iskandar Muda.
Penulis bernama T. Muhammad Shandoya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2017.
Editor: Nurul Hasanah